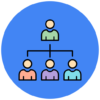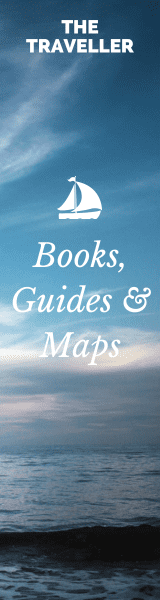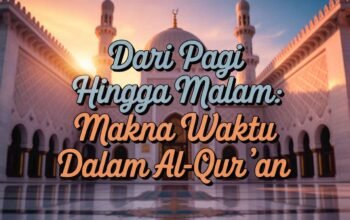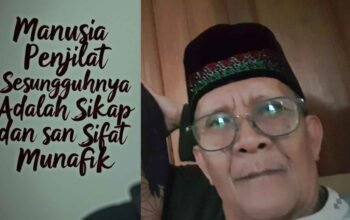ppmindonesia.com, Jakarta-Luas total wilayah provinsi-provinsi di Pulau Jawa mencapai 132.603,58 kilometer persegi. Sementara itu, wilayah provinsi-provinsi di Pulau Papua lebih dari tiga kali lipat lebih besar, yaitu 412.214,62 kilometer persegi (BPS, 2024). Pulau Jawa, yang sangat padat penduduknya, memiliki kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia, khususnya di Provinsi Daerah Khusus Jakarta, yang mencatatkan 16.165 orang per kilometer persegi pada tahun 2024.
Sebaliknya, kepadatan penduduk di Pulau Papua sangat rendah, dengan Provinsi Papua Barat tercatat hanya memiliki 10 orang per kilometer persegi, sedangkan provinsi-provinsi lain di Papua seperti Papua Barat Daya (16 orang per kilometer persegi), Papua (13 orang per kilometer persegi), Papua Selatan (5 orang per kilometer persegi), Papua Tengah (24 orang per kilometer persegi), dan Papua Pegunungan (29 orang per kilometer persegi), semuanya menunjukkan tingkat kepadatan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan Pulau Jawa.
Seiring dengan upaya pemerintah untuk mencapainya, salah satu program utama yang sedang digagas oleh Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah swasembada pangan, yang akan melibatkan pembukaan lahan pertanian di Pulau Papua.
Pemerintah berencana membuka hutan seluas 2 juta hektare untuk pengembangan lumbung pangan dan 1 juta hektare lainnya untuk pengembangan bioenergi. Selain itu, ada rencana untuk melanjutkan program transmigrasi yang sudah berjalan sebelumnya.
Namun, rencana tersebut mendapat penolakan keras dari berbagai kalangan di Papua, termasuk anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Papua, Dewan Gereja Papua, organisasi lingkungan seperti Greenpeace dan Walhi, Majelis Rakyat Papua (MRP), serta perwakilan masyarakat yang memiliki hak ulayat dan hak adat.
Mereka memandang program transmigrasi, yang dalam banyak kasus melibatkan perpindahan penduduk luar daerah, sebagai ancaman terhadap eksistensi budaya dan hak-hak masyarakat adat Papua. Mereka khawatir bahwa migrasi besar-besaran akan berujung pada perampasan tanah adat, kerusakan lingkungan, dan pengusiran masyarakat asli Papua.
Potensi Konflik Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Rencana untuk membuka hutan seluas 3 juta hektare—setara dengan 300 kilometer persegi—dapat dianggap tidak berdampak besar terhadap luas daratan Pulau Papua, yang masih tersisa 411.914,62 kilometer persegi setelah pemanfaatan lahan tersebut.
Namun, meskipun tidak ada pengurangan signifikan terhadap luas wilayah daratan, proyek ini berpotensi menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang jauh lebih besar. Para pemangku kepentingan menilai bahwa pembukaan hutan tropis untuk pertanian dan industri bioenergi berisiko memperburuk kerusakan lingkungan, termasuk penghilangan karbon biomassa yang mengarah pada peningkatan suhu udara dan deforestasi yang lebih luas. Ketegangan ini berpotensi memicu konflik terkait pengelolaan sumber daya alam, pemanfaatan tanah, dan hak-hak masyarakat adat.
Selain itu, ada kekhawatiran bahwa migrasi transmigran yang berasal dari luar Papua—meskipun Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menegaskan bahwa tidak ada transmigrasi luar daerah yang akan dilakukan—tetap dapat memicu ketegangan sosial, terutama jika transmigran berasal dari suku-suku atau daerah lain di Indonesia.
Transmigrasi ini, meskipun diperkirakan hanya akan melibatkan perpindahan masyarakat lokal dalam skala kecil, tetap dianggap sebagai ancaman terhadap identitas budaya masyarakat asli Papua.
Program Transmigrasi: Pandangan dan Pola yang Pernah Diterapkan di Papua
Selama ini, program transmigrasi di Papua telah dilaksanakan dalam berbagai bentuk. Berdasarkan catatan sejarah, sejak masa kolonial Belanda hingga era Orde Baru dan seterusnya, ada berbagai pola transmigrasi yang dikembangkan di Papua. Beberapa pola yang pernah diterapkan meliputi:
- Pola Tanaman Pangan: Sebagian besar program transmigrasi (lebih dari 90 persen) pada masa itu berfokus pada pengembangan tanaman pangan, terutama padi. Setiap keluarga transmigran diberikan lahan pertanian seluas dua hektare yang terbagi menjadi lahan pekarangan, lahan usaha, dan lahan hutan untuk pengolahan pertanian.
- Pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR Trans): Program ini bertujuan untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit dan lainnya. Di beberapa daerah, seperti Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Jayapura, pengembangan perkebunan dengan pola PIR ini melibatkan perusahaan inti yang bekerja sama dengan masyarakat transmigran untuk mengelola lahan.
- Pola Nelayan: Pola ini difokuskan pada daerah pesisir dengan program transmigrasi yang disiapkan untuk nelayan dan pengembangan industri perikanan. Salah satu kawasan yang mengembangkan pola ini adalah di Kabupaten Biak Numfor.
- Pola Hutan Tanaman Industri (HTI Trans): Program ini memanfaatkan komoditas tanaman sagu yang dikembangkan di beberapa kawasan, seperti Kabupaten Manokwari.
- Pola Jasa dan Industri (Trans Jastri): Pola ini berfokus pada pengembangan industri berbasis sumber daya alam lokal, seperti pemanfaatan galian C dan industri kayu.
Selain pola-pola tersebut, ada pula program Transmigrasi Bhineka Tunggal Ika (Trans Bhintuka) yang diluncurkan oleh Menteri Transmigrasi Jenderal (Purn) Hendro Priyono pada masa Orde Baru. Program ini bertujuan untuk memperkuat integrasi nasional di wilayah Papua dan Aceh dengan memindahkan masyarakat dari luar ke dua wilayah tersebut, meskipun pada masa itu program ini menuai kritik dan kontroversi.
Fokus Pemerintah dan Penolakan Masyarakat Adat
Meskipun berbagai pola transmigrasi di Papua telah terbukti mengubah lanskap alam dan masyarakat, saat ini pemerintah berfokus pada revitalisasi kawasan transmigrasi yang sudah ada, terutama yang tercatat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN). Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menyatakan bahwa, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, tidak ada perpindahan penduduk dari luar Papua ke wilayah tersebut. Program ini, jika dilanjutkan, hanya akan melibatkan transmigrasi lokal untuk memenuhi kebutuhan pengembangan daerah yang lebih terencana dan terarah.
Namun, meskipun program transmigrasi lokal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, banyak pihak masih menilai bahwa pengembangan kawasan transmigrasi yang melibatkan konversi lahan hutan menjadi areal pertanian dan perkebunan berisiko menimbulkan ketegangan sosial dan lingkungan yang serius.
Oleh karena itu, dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat adat serta pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk memastikan bahwa program-program ini tidak hanya menguntungkan bagi masyarakat luar Papua, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem dan hak-hak masyarakat adat di Papua.(asyary)