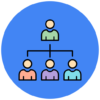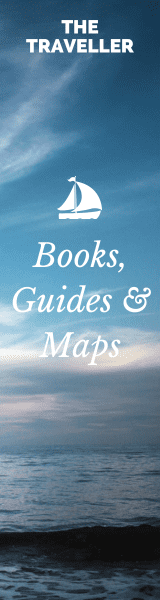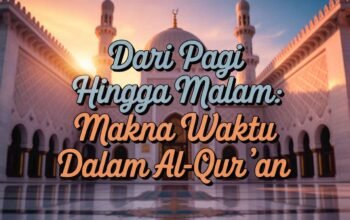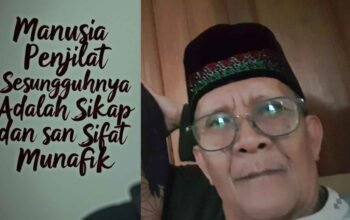ppmindonesia.com.Jakarta – Laksana dua lukisan yang menggambarkan pemandangan yang sama namun dengan palet warna yang kontras, begitulah perdebatan sengit yang kini mencuat ke permukaan perihal angka kemiskinan di Republik ini.
Di satu sisi, Badan Pusat Statistik (BPS) dengan bangga menampilkan potret kemiskinan yang terkelola, hanya menyentuh 8,57 persen penduduk per September 2024. Sebuah angka yang memberikan secercah harapan akan keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan.
Namun, narasi optimis ini seketika tergerus oleh laporan setajam belati dari Bank Dunia. Lembaga keuangan internasional itu tanpa ragu menampilkan visualisasi yang jauh berbeda, sebuah lanskap kemiskinan yang membentang luas, menjangkau 60,3 persen populasi Indonesia pada tahun 2024. Angka fantastis yang setara dengan 171,8 juta jiwa, sebuah ironi di tengah gembar-gembor pertumbuhan ekonomi.
Perbedaan yang menganga ini bukan sekadar selisih angka statistik belaka. Ia adalah jurang interpretasi yang mempertanyakan fondasi pemahaman kita tentang kemiskinan di negeri ini. Apakah realita kemiskinan di Indonesia sejinak yang digambarkan BPS, ataukah ia adalah monster tersembunyi yang mengintai di balik gemerlap angka makroekonomi?
Para ekonom angkat bicara, mencoba menjernihkan kabut perbedaan metodologis yang melatari kedua laporan tersebut. Standar garis kemiskinan menjadi pangkal persoalan. BPS dengan metodologinya sendiri, menetapkan batasan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan patokan global yang digunakan Bank Dunia.
Bank Dunia, dengan merujuk pada paritas daya beli (PPP) dan status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas, menggunakan standar US$6,85 per orang per hari – sebuah angka yang terasa jauh lebih relevan dengan biaya hidup yang kian merangkak naik.
Wijayanto Samirin dari Universitas Paramadina melihat perbedaan ini bukan sebagai pertentangan yang harus dimenangkan salah satu pihak. Ia justru menawarkan solusi pragmatis: merangkul kedua perspektif. Menggunakan dua garis kemiskinan sekaligus dalam beberapa tahun ke depan, menurutnya, dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan akurat tentang kompleksitas kemiskinan di Indonesia.
Namun, di balik perdebatan metodologi, tersembunyi implikasi kebijakan yang mendasar. Bhima Yudhistira dari Celios mengingatkan bahwa jika pemerintah terpaku pada angka kemiskinan BPS yang rendah, kebijakan perlindungan sosial yang dirancang pun akan menjadi terlalu sempit, gagal menjangkau jutaan masyarakat rentan yang sebenarnya berada di bawah garis kesejahteraan yang layak.
Suara dari parlemen pun turut bergaung. Saadiah Uluputty, anggota Komisi IV DPR RI, dengan nada prihatin menyoroti ketidakselarasan data ini, terutama dampaknya pada sektor-sektor yang menjadi tumpuan hidup masyarakat miskin di pedesaan, pesisir, dan kepulauan.
Baginya, perbedaan angka ini bukan sekadar urusan statistik, melainkan cerminan dari keberpihakan negara yang patut dipertanyakan. Pertumbuhan sektor pertanian yang gemilang pun terasa hambar jika tidak mampu dirasakan oleh petani kecil yang masih berkutat dengan masalah klasik.
Laporan Bank Dunia, meskipun terasa pahit, mungkin adalah alarm yang membangunkan. Ia memaksa kita untuk meninjau kembali definisi kemiskinan yang kita anut, untuk merenungkan apakah standar yang kita gunakan selama ini sudah cukup relevan dengan realita kehidupan masyarakat.
Di antara dua data yang saling bertolak belakang ini, mungkin tersembunyi sebuah kebenaran yang lebih kompleks, sebuah realita kemiskinan yang jauh lebih dalam dan luas dari yang selama ini kita akui. Pertanyaannya kini, beranikah kita membuka mata sepenuhnya dan merumuskan kebijakan yang benar-benar berpihak pada mereka yang selama ini mungkin terlewatkan oleh bingkai statistik yang terlalu sempit? (emha)