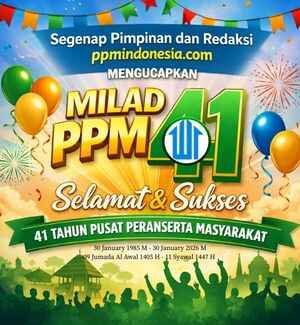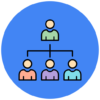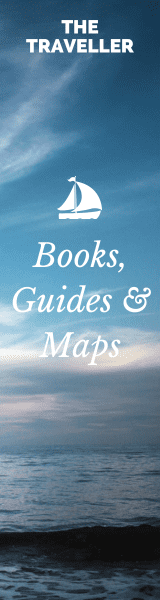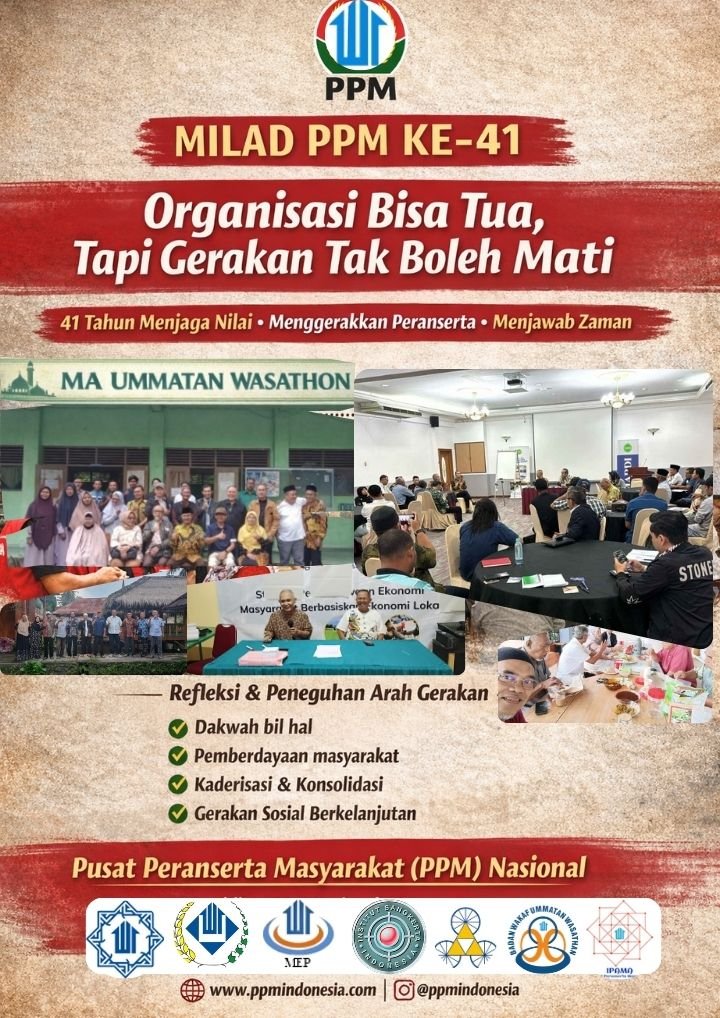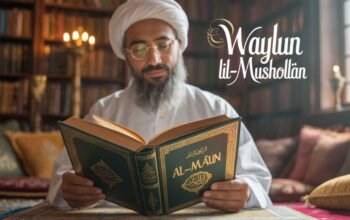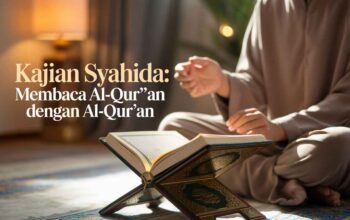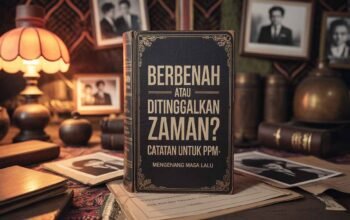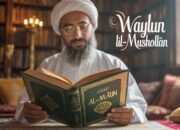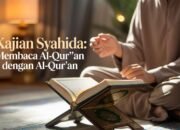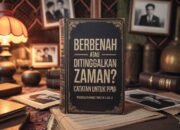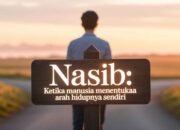ppmindonesia.com.Jakarta – Di jantung pulau Kalimantan, bersemayam sebuah peradaban tua yang telah hidup berdampingan dengan alam selama ribuan tahun. Suku Dayak, penghuni asli pulau ini, bukan hanya dikenal lewat rumah panjang, ukiran kayu, atau senjata tradisionalnya, tetapi juga melalui filosofi hidup yang penuh kearifan dan keselarasan dengan alam semesta.
Asal Usul yang Sarat Makna
Nama “Dayak” secara historis digunakan oleh para penjelajah dan misionaris Eropa untuk menyebut suku-suku pedalaman Kalimantan. Namun, dalam realitasnya, Suku Dayak terdiri dari ratusan sub-etnis seperti Ngaju, Iban, Kayan, Kenyah, Ma’anyan, dan masih banyak lagi—masing-masing memiliki bahasa, budaya, serta sistem adat tersendiri.
Bagi mereka, tanah bukan hanya ruang hidup, tetapi juga warisan spiritual. “Kami percaya tanah ini bukan milik kami. Kami hanya dijadikan penjaganya oleh leluhur,” tutur Andius Tawai, tokoh adat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah.
Cerita asal-usul Dayak tersebar dalam bentuk mitos dan legenda yang diwariskan secara lisan. Sebagian besar kisah itu menggambarkan hubungan manusia dengan roh alam dan leluhur, mencerminkan kepercayaan animistik yang menyatu dalam kehidupan sehari-hari.
Simbol Kehidupan: Rumah Betang dan Seni Ukir
Salah satu simbol utama budaya Dayak adalah rumah betang—rumah panjang yang dihuni secara komunal. Rumah ini bukan sekadar tempat tinggal, tetapi juga pusat kehidupan sosial, tempat berlangsungnya musyawarah, upacara adat, hingga perayaan panen.
Di sisi lain, seni ukir dan tato menjadi cermin nilai-nilai spiritual dan identitas pribadi. Ukiran kayu penuh motif flora-fauna tidak hanya memanjakan mata, tapi juga membawa makna filosofis—seperti perlindungan, kekuatan, atau hubungan manusia dengan dunia gaib.
“Setiap motif punya cerita,” jelas Lio Jatu, seniman ukir Dayak Kenyah. “Kami tidak membuat seni untuk hiasan, tapi untuk menjaga hubungan dengan roh alam.”
Kearifan Adat yang Menjaga Alam
Salah satu nilai paling penting dalam budaya Dayak adalah prinsip hidup harmonis dengan alam. Mereka punya hukum adat yang mengatur penggunaan hutan, sungai, dan lahan pertanian.
Misalnya, ada larangan membuka lahan dekat sumber mata air, atau aturan berpindah ladang untuk memberi waktu bagi tanah memulihkan diri.
Sistem ini dikenal sebagai huma berpindah dan sering disalahpahami sebagai praktik yang merusak. Padahal, menurut banyak penelitian, metode ini justru menjaga keberlanjutan hutan dalam jangka panjang.
“Orang luar sering anggap kami tidak modern,” ungkap Yenika Bala, pegiat komunitas adat Dayak Iban. “Padahal, hukum adat kami lebih dulu bicara tentang konservasi sebelum istilah itu populer.”
Tantangan Modern dan Ancaman Budaya
Namun, kemajuan zaman membawa tantangan serius. Masuknya tambang, perkebunan sawit, dan proyek infrastruktur membuat banyak komunitas Dayak kehilangan lahan adat. Bersamaan dengan itu, pewarisan budaya kepada generasi muda mulai terputus.
Pendidikan formal yang tidak inklusif terhadap budaya lokal membuat anak-anak Dayak lebih mengenal tokoh nasional ketimbang pahlawan leluhur mereka. Bahasa daerah pun perlahan ditinggalkan.
“Kalau tidak kita rawat, budaya ini bisa hilang dalam satu generasi,” kata Johan Lahing, guru sekaligus pegiat dokumentasi budaya di Kapuas Hulu.
Menyambung Masa Lalu dan Masa Depan
Meskipun begitu, masih ada harapan. Beberapa komunitas Dayak kini aktif mendokumentasikan ritual dan bahasa dalam bentuk digital.
Festival budaya Dayak juga mulai digelar kembali, mempertemukan generasi tua dan muda dalam semangat merawat warisan bersama.
“Kami tidak ingin kembali ke masa lalu,” ujar Johan. “Kami hanya ingin masa depan yang tidak melupakan akar kami.”
Dalam semangat itu, jelajah budaya Dayak bukan hanya sebuah perjalanan ke masa silam, tapi juga refleksi tentang bagaimana Indonesia seharusnya memandang kekayaan budayanya sendiri—bukan sebagai ornamen, melainkan sebagai pondasi nilai yang relevan hingga hari ini.((acank)