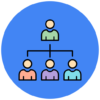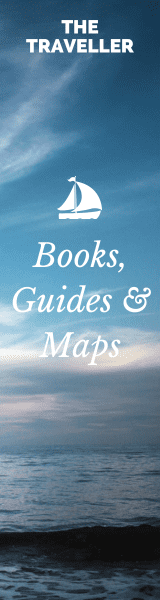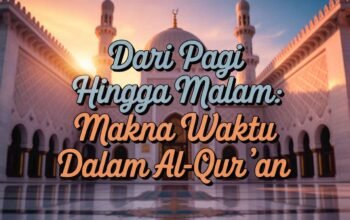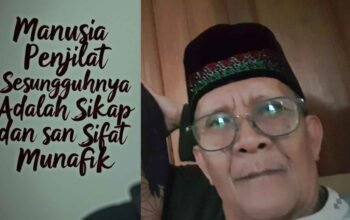ppmindonesia.com.Jakarta – Setiap kali bulan Rabi’ul Awal tiba, denyut budaya Islam dan tradisi Jawa menyatu dalam sebuah perayaan meriah dan sakral yang masih bertahan ratusan tahun: Sekaten.
Dari halaman megah Masjid Gedhe Kasunanan Surakarta hingga alun-alun utara Keraton Yogyakarta, genderang gamelan pusaka ditabuh, doa-doa dilantunkan, dan ribuan warga berkumpul dalam semangat yang sama: memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW.
Namun Sekaten bukan sekadar pesta rakyat. Ia adalah jejak nyata bagaimana Islam datang ke Nusantara—bukan dengan pedang dan kekuasaan, melainkan melalui kesenian, budaya, dan pendekatan lokal yang memikat.
Sekaten adalah wujud konkret dari strategi dakwah Wali Songo, terutama Sunan Kalijaga, yang dengan arif menyisipkan nilai-nilai Islam ke dalam denyut kehidupan masyarakat Jawa.
Warisan Sunan Kalijaga
Menurut sejarawan Islam Jawa, Dr. Ahmad Zainul Fanani dari UIN Sunan Kalijaga, Sekaten merupakan contoh keberhasilan Islamisasi yang tidak destruktif. “Islam hadir bukan untuk mengganti kebudayaan lokal, tetapi menjiwainya.
yang digunakan dalam Sekaten dulunya adalah alat pemikat massa agar berkumpul, lalu mereka dikenalkan pada syahadatain. Ini dakwah dengan rasa, bukan sekadar kata,” ujarnya.
Nama “Sekaten” sendiri dipercaya berasal dari kata syahadatain—dua kalimat syahadat yang menjadi inti ajaran Islam. Seiring waktu, nama itu mengalami pelokalan menjadi “sekaten,” yang dalam tafsir budaya Jawa juga bisa berarti suka ati (senang hati), atau sekati (menimbang yang baik dan buruk).
Penafsiran ini menunjukkan bagaimana dakwah Islam waktu itu tidak membenturkan, tapi menyerap dan menyesuaikan diri dengan kebudayaan lokal.
Kesamaan dan Perbedaan: Solo dan Jogja
Meski sama-sama berasal dari akar budaya Mataram Islam, Sekaten di Keraton Surakarta dan Yogyakarta memiliki kekhasan masing-masing. Keduanya menggelar pasar malam sebulan penuh, menampilkan gamelan pusaka keraton, dan ditutup dengan grebeg mulud—pawai gunungan berisi hasil bumi yang kemudian diperebutkan warga sebagai simbol berkah dan sedekah raja.
Namun, seperti disampaikan oleh budayawan Yogyakarta, KRT Jatiningrat, ada nuansa simbolik yang membedakan: “Di Yogyakarta, prosesi udik-udik, pembacaan riwayat Nabi, hingga kundur gongso (pengembalian gamelan ke keraton) mempertegas sisi religius dan spiritual Sekaten. Sementara di Solo, kekuatan estetika dan suasana syukur rakyat lebih menonjol.”
Jogja memainkan gamelan Kyai Gunturmadu dan Kyai Nogowilogo setelah salat Isya, dengan iringan semangat spiritual yang kental. Sultan hadir, berdoa, menebar udik-udik—beras, koin, dan bunga sebagai simbol kemurahan hati raja.
Sedangkan di Solo, prosesi Miyos Gangsa dan Tumplak Wajik menjadi kekayaan tersendiri, memperkuat ikatan antara rakyat dan budaya agraris yang mengakar.
Islam Nusantara yang Membumi
Tradisi Sekaten adalah saksi bahwa Islam tidak datang untuk menyingkirkan kearifan lokal, melainkan menyuburkannya. Di tengah tantangan modernisasi, komersialisasi budaya, hingga arus dakwah tekstual yang kaku,
Sekaten justru menunjukkan bahwa spiritualitas bisa bersemayam dalam pertunjukan gamelan, dalam gunungan ketan dan sayuran, dalam alun-alun yang dipenuhi rakyat.
“Islam Nusantara adalah Islam yang merangkul, bukan memukul,” kata KH Mustofa Bisri (Gus Mus) dalam sebuah wawancara. “Dan Sekaten adalah bukti sejarah bahwa dakwah dengan kelembutan lebih mengakar di hati rakyat ketimbang ceramah yang menggertak.”
Dengan nilai-nilai tersebut, Sekaten bukan sekadar tradisi—ia adalah strategi kultural yang cerdas dan damai. Ia memperlihatkan bagaimana Islam diterima dengan hati terbuka oleh masyarakat yang sebelumnya menganut Hindu-Buddha, bukan karena dogma, tapi karena dialog yang bersahabat dengan budaya.
Menjaga Nafas Tradisi
Hari ini, di tengah sorotan pariwisata dan pasar malam yang kadang lebih riuh ketimbang makna religiusnya, Sekaten menghadapi tantangan: bagaimana agar ia tidak kehilangan ruhnya sebagai perayaan spiritual dan dakwah kebudayaan?
Pemerintah daerah dan keraton memiliki peran penting menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan penguatan nilai-nilai Islam yang membentuk jantung tradisi ini.
Pendidikan berbasis kearifan lokal, dokumentasi sejarah, hingga keterlibatan generasi muda dalam memahami makna Sekaten menjadi agenda penting.
Sebagaimana kalimat yang sering diperdengarkan dalam prosesi Sekaten: “Ora ilok gumunggung, aja ngapusi, aja dumeh, lan kudu eling lan waspada.” (Tidak boleh sombong, jangan menipu, jangan sewenang-wenang, dan harus selalu ingat dan waspada).
Nilai-nilai inilah yang menjadikan Sekaten bukan hanya upacara budaya, tapi juga pelajaran moral bagi umat dan bangsa.(acank)