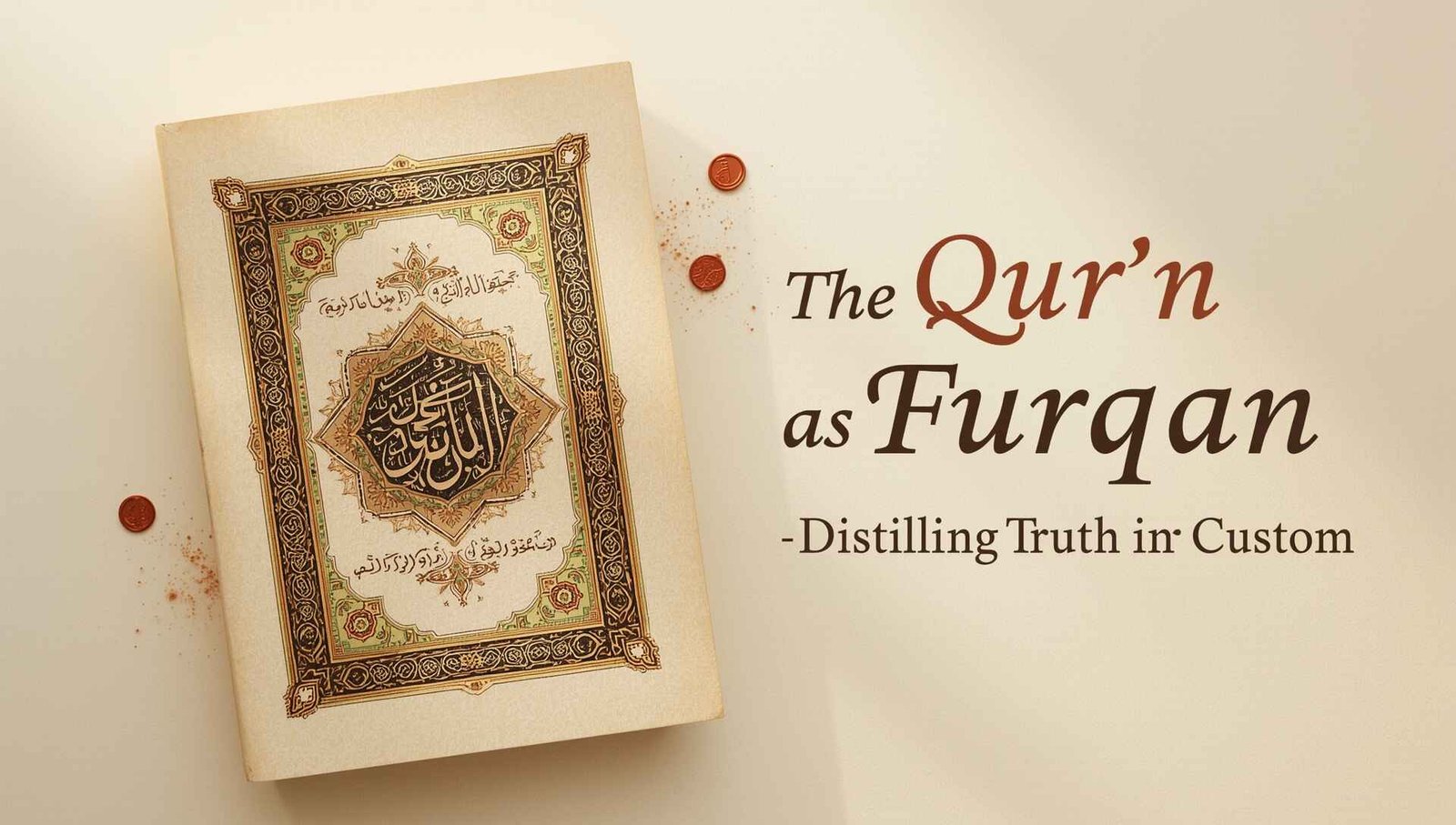ppmindonesia.com.Jakarta – Dalam suasana keagamaan yang semakin ritualistik, umat Islam hari ini dihadapkan pada kenyataan pahit: banyak praktik keagamaan yang dijalankan justru bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur’an.
Menyadari hal itu, penting kiranya untuk kembali memahami fungsi Al-Qur’an sebagai furqan — pembeda antara yang benar dan yang salah, antara yang hakiki dan yang keliru.
Dalam kajian tematik yang disampaikan melalui Kanal Syahida, Husni Nasution menyoroti bahwa realitas umat menunjukkan keterputusan antara ajaran yang diyakini dengan petunjuk wahyu yang sebenarnya.
Banyak umat yang hanya menjadikan Al-Qur’an sebagai bacaan ritual, bukan sebagai rujukan dalam menyaring keyakinan dan praktik keagamaannya. Padahal, dalam Qur’an Surah Al-Anfal ayat 29, Allah berjanji:
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا… ٢٩
“Jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan…”
Artinya, furqan adalah anugerah bagi orang bertakwa, yaitu kemampuan untuk memilah antara yang haq dan batil — kemampuan yang kini sangat langka dalam lanskap keagamaan kita.
Menyimak Ketidaksesuaian Praktik dengan Wahyu
Sebagai contoh, Qur’an Surah Qaf ayat 45 memerintahkan:
…فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِࣖ ٤٥
“Berilah peringatan dengan Al-Qur’an kepada orang yang takut kepada ancaman-Ku.”
Namun kenyataannya, sebagian besar bentuk peringatan dalam masyarakat justru tidak bersumber dari Al-Qur’an. Yang diangkat bukan pesan wahyu, melainkan kisah-kisah turun-temurun, simbol mistik, atau bahkan ketakutan buatan. Ini menunjukkan bagaimana Al-Qur’an kerap dipinggirkan dari peran utamanya sebagai sumber peringatan dan petunjuk hidup.
Hal serupa terjadi dalam pelaksanaan shalat. Dalam Qur’an Surah Al-Isra ayat 110, terdapat perintah agar tidak menjaharkan suara dalam shalat secara berlebihan:
…وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ١١٠
“Janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan jangan pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah…”
Namun praktik di banyak tempat justru menjaharkan tanpa memperhatikan batas dan konteks, seolah ayat ini tidak pernah ada. Ini menandakan lemahnya fungsi furqan dalam menilai dan menimbang praktik yang sudah dianggap wajar.
Antara Anggapan Umum dan Ketetapan Wahyu
Pemahaman tentang shadaqah juga menjadi sorotan. Umat Islam banyak yang memandangnya sebagai amalan sunnah — sebuah bentuk kebaikan sukarela. Namun, dalam Qur’an Surah At-Taubah ayat 60, ditegaskan bahwa shadaqah adalah kewajiban yang ditetapkan oleh Allah:
“Itu adalah kewajiban dari Allah (faridhatan minallah).”
Demikian pula dengan status Al-Qur’an itu sendiri. Sebagian umat memahaminya hanya sebagai kitab suci yang dibaca untuk keberkahan, padahal dalam Qur’an Surah Al-Qashash ayat 85, ditegaskan bahwa Al-Qur’an adalah risalah kerasulan yang diwajibkan untuk disampaikan.
Mengkritisi Narasi Tawar-Menawar Syariat
Salah satu narasi populer di tengah umat adalah cerita tentang tawar-menawar jumlah shalat dari 50 waktu menjadi 5 waktu saat peristiwa Isra’ Mi’raj. Cerita ini jika tidak ditimbang dengan furqan, dapat menimbulkan persepsi bahwa syariat bisa dinegosiasikan. Padahal, Qur’an Surah Al-Ahzab ayat 38 menegaskan:
“Tidak ada keberatan bagi Nabi terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Itulah sunnatullah yang berlaku sejak dahulu.”
Ketetapan Allah, menurut ayat ini, bersifat pasti, terukur, dan tidak dapat diubah. Maka, kisah tawar-menawar itu patut dilihat secara kritis melalui kaca mata furqan, agar umat tidak terjebak dalam anggapan yang merusak makna ketundukan kepada syariat.
Kembali kepada Furqan
Kajian ini mengajak umat untuk kembali kepada Al-Qur’an sebagai furqan, bukan sekadar sebagai bacaan, tetapi sebagai alat ukur utama dalam beragama. Tanpa furqan, umat akan terus berjalan dalam kabut: mengira benar padahal keliru, merasa cukup padahal kosong, dan menjalankan agama tanpa pondasi wahyu yang kokoh.
Sebagaimana disampaikan Husni Nasution, ketakwaan adalah kunci untuk mendapatkan furqan, karena dengan takwa, hati akan dibuka, akal akan tajam, dan pandangan terhadap kebenaran akan jernih. Inilah saatnya menjadikan Al-Qur’an bukan hanya bacaan, tetapi standar penilaian — menyaring kebenaran dari kebiasaan.(husni fahro).
*Husni Fahro, seorang pemikir kebangsaan dan pengkaji Al-Qur’an asal Bogor. Alumni IAIN Sumatera Utara ini dikenal dengan gagasannya tentang Nasionalisme Religius dan kepeduliannya pada isu-isu solidaritas sosial.”