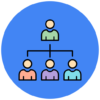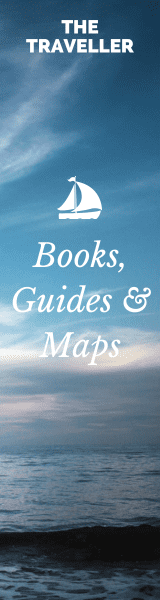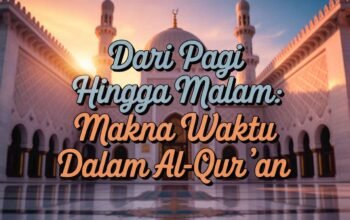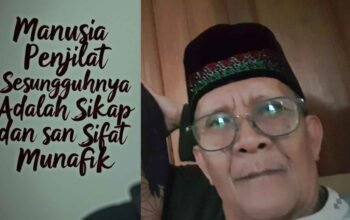Sukarno
Oleh: *Ali Musatafa Trajutisna
Siang itu udara terasa berat. Angin berputar seperti orang mabuk, mengibaskan debu dan jelaga kendaraan ke mana-mana. Sri pulang sebelum lohor. Ia ingin menuntaskan laporan penelitian tentang naskah-naskah tua koleksi Pustaka Pura Paku Alaman.
Sudah tiga bulan ia bergelut dengan kitab-kitab berwarna kuning kelabu itu, sampai paru-parunya terasa mampat, napasnya pendek-pendek, dan batuk kecil tak mau pergi.
Suaminya, H. Sukarno, B.A., justru senang bila Sri mendendangkan gending Jawi ketika menyalin teks. Padahal bagi Sri, nada-nada itu hanya menambah sakit di kepala.
Begitu mobilnya berhenti di depan rumah, Karno sudah berdiri di pagar. Tangannya menenteng map biru bertuliskan spidol tebal: Nero van Java — Prof. Dr. Sri Martani Sukarno.
Sri tahu, badai kecil akan segera tiba.
Ia turun, menunduk, mencium tangan suaminya dengan takdzim. Tapi Karno tak membalas. Ia menatap Sri waspada, seperti penjaga yang menduga akan ada pelanggaran.
“Sekedap, nggih, Kangmas,” ucap Sri pelan. “Shalat dulu.”
“Kita bicara dulu!”
Sri menatapnya. “Ada apa?”
“Kau tahu maksudku.”
Tanpa menunggu jawaban, Karno meletakkan map biru itu di meja tamu dengan hentakan.
“Untuk apa kamu ungkit sejarah yang bisa menimbulkan fitnah! Hanya membuat umat dan kraton saling curiga!”
“Lho, dos pundi tho? Ada datanya kok.”
“Aku sudah baca! Itu sumber Belanda, kan?”
“Iya. Tapi—”
“Penjajah sampai dunia kiamat jangan dipercaya!”
Sri menarik napas dalam. “Kangmas, saya bekerja berdasar kaidah ilmiah. Tugas sejarawan adalah menelusuri konteks masa lalu dan dampaknya hari ini. Sejak Sultan Agung hingga raja-raja sekarang, semua bergelar Sayidin Panata Gama Kalifatullah, kecuali Amangkurat I. Bukankah menarik jika kita telusuri kenapa?”
“Cukup!” potong Karno. “Aku mau ngajar!”
Ia bergegas keluar, meninggalkan Sri duduk di sofa, menatap map biru itu lama-lama. Suaminya memang lelaki yang telaten dan bertanggung jawab—rapi mengatur uang rumah tangga, disiplin menunaikan shalat berjamaah, bahkan selalu hormat bendera sebelum berangkat kerja. Bagi Karno, Garuda dan Merah Putih adalah lambang suci, tak boleh dijadikan bahan olok atau tulisan ilmiah.
Sri pernah menulis esai tentang kebiasaan itu dan dimuat di jurnal luar negeri. Ia menganalisisnya dari sudut pandang sejarah kebudayaan Denys Lombard. Tapi begitu tahu, Karno memaksanya hormat bendera tiga kali dan mencium Merah Putih tiga kali.
Sejak itu Sri hanya bisa tersenyum getir setiap kali mengenangnya.
Mereka tumbuh di desa yang sama, di lereng perbukitan Kulon Progo. Sejak SD hingga SMA duduk di sekolah yang sama. Karno dua tahun lebih tua, dan selalu menjadi pelindungnya: membonceng Sri ke sekolah, mengajari naik sepeda, bahkan membela jika ada yang mengganggu.
Setelah SMA, Karno kuliah di Jurusan Sejarah Yogyakarta. Sri sempat berhenti setahun karena tak ada biaya, hingga Karno datang menemui ibunya.
“mBok, saya kuliah ini hanya banda keberanian,” katanya lirih.
Ibunya Sri memandang Karno lama, lalu berkata pelan, “Bawalah Sri ke Yogya. Aku titipkan.”
Sejak itu mereka hidup berdekatan, tapi tetap terpisah. Masing-masing menempati kamar kecil di dekat Kali Code. Suatu sore Karno datang membawa lamaran.
“Dengan hidup bersama, kita bisa lebih hemat,” katanya.
Sri terdiam. Di kepalanya, angin sungai seperti berdesir membawa kabar dari masa depan.
Ia menunduk, bingung antara malu dan bahagia.
“Dik Sri tetap kuliah,” kata Karno lagi. “Aku yang akan bekerja.”
“Tapi Mas tidak kuliah?”
“Nanti, setelah mapan.”
Sri menatapnya. “Tidak! Mas harus terus kuliah. Aku yang akan bekerja.”
Butuh waktu tiga bulan untuk meyakinkan Sri, hingga akhirnya mereka menikah. Karno benar-benar berhenti kuliah, bekerja sebagai guru sejarah di Prambanan. Sri justru melesat: lulus summa cum laude, lalu mendapat beasiswa ke Sorbonne.
Tiga tahun di Paris, ia meraih gelar doktor. Ia melahirkan anak kedua di sana—Rani—yang disebut suaminya Noviantini Maharani.
Sepulang dari Eropa, Sri menjadi profesor sejarah di kampus ternama. Di papan nama rumah dinasnya tertulis:
H. Sukarno, B.A.
Di Lasem, angin laut berbau asin. Sri berdiri di tepi pantai, menatap jauh ke utara. Ia sedang meneliti kembali jejak ekspedisi Cheng Ho. Catatannya menyebutkan bahwa banyak peranakan Tionghoa yang menjadi bagian penting gelombang Islamisasi awal.
Ketika Karno tahu, ia marah besar.
“Tidak penting itu benar atau tidak! Tidak pantas dikatakan kita jadi muslim karena orang Cina!”
“Tapi ada bukti sejarah, Kangmas. Banyak wali keturunan Cina.”
“Jangan bawa-bawa Cina! Islam itu dari Arab!”
Sri menghela napas. “Yang bicara ini Sri, sejarawan. Bukan sekadar istrimu.”
“Justru karena kau istriku, aku mengingatkan: jangan sampai ilmumu menodai iman!”
Langit Lasem meredup. Ombak pecah di batu-batu, membawa gema yang panjang. Di bawah cahaya senja, Sri tahu betapa sulitnya menjadi ilmuwan perempuan di hadapan suami yang memuja kesakralan tradisi.
Beberapa tahun kemudian, di Paris, salju tipis memutih di atap-atap kota. Sri datang menghadiri pemakaman Madame René—istri dosennya dulu. Di antara hadirin, hanya Sri yang menangis. Setelah upacara selesai, seorang kolega lamanya, Profesor Donny Raphael, mengantarnya pulang.
Sampai di depan kamar hotel, Donny menatapnya lama.
“I have to kiss you,” katanya pelan.
Sri mundur, tapi tubuhnya terpojok.
“Please, Don’t—”
Terlambat. Ciuman panas itu datang seperti badai. Sri menepis, menggigit bibir Donny, lalu menamparnya keras.
“How dare you!”
Pintu dibanting. Sri jatuh di kursi, menggigil.
Ia menatap langit-langit kamar yang putih dingin, lalu berbisik lirih, “Duh, Kangmas… aku tetap istrimu, tapi aku juga seorang ilmuwan. Keduanya tak mungkin kupisahkan selamanya.”
Sekembalinya dari Paris, tubuh Sri melemah. Ia dirawat di rumah sakit. Ketika Profesor Sumarti, sahabatnya, menjenguk, Sri berbicara pelan:
“Sum, aku sudah putuskan. Aku harus berdiri sebagai ilmuwan, bukan sekadar istri.”
Sumarti menatapnya tajam. “Untuk apa, Sri? Kau mau melawan suamimu?”
“Bukan melawan. Tapi menegakkan kebenaran ilmiah. Sejarah bukan kitab suci.”
“Dan harga yang kau bayar?”
Sri tersenyum tipis. “Adalah diriku sendiri.”
Lampu rumah sakit berkedip. Di luar jendela, senja jatuh di balik Gunung Merapi—seakan ikut menyaksikan seorang perempuan yang memilih berdiri di antara cinta dan kebenaran, di antara suami dan sejarah.
Hari-hari Sri di rumah sakit seperti lembar-lembar kertas yang perlahan pudar. Tubuhnya melemah, tapi pikirannya tetap tajam. Setiap pagi ia menulis di buku catatan kecil, menandai tanggal dan menulis kalimat singkat:
“Sejarah adalah ingatan manusia terhadap dirinya sendiri. Siapa yang takut pada sejarah, sesungguhnya takut pada bayangannya.”
Karno datang setiap sore, membawa buah tangan: jambu, pisang, atau majalah agama. Ia duduk di tepi ranjang, diam. Kadang hanya membaca ayat-ayat pendek, lalu menatap istrinya dengan mata yang penuh sayang tapi juga letih.
“Kau masih menulis?” tanyanya suatu kali.
Sri tersenyum lemah. “Menulis itu seperti bernapas, Kangmas. Kalau berhenti, aku mati.”
Karno menunduk, memegang tangan istrinya yang dingin. “Tapi jangan sampai tulisanmu memisahkan kita.”
“Yang memisahkan kita bukan tulisan,” bisik Sri, “tapi dinding di kepalamu.”
Beberapa bulan kemudian, Sri wafat.
Ia dimakamkan di pemakaman kecil di dekat kampus, di antara pohon flamboyan yang sedang berbunga merah menyala. Banyak dosen dan mahasiswa datang. Karno berdiri paling depan, tubuhnya tegak seperti patung, matanya kering.
Di nisan marmer putih tertulis:
Prof. Dr. Sri Martani Sukarno (1953–2004)
“Ilmu adalah jalan pulang menuju cahaya.”
Setelah semua pulang, Karno duduk lama di tepi makam. Ia membuka map lusuh yang selama ini disimpannya diam-diam. Di dalamnya ada surat Sri, tertulis dengan tinta biru lembut:
“Kangmas,
Jika suatu saat kau membaca surat ini, mungkin aku sudah tak ada.
Aku tahu cintamu besar, tapi cintamu pada ketertiban lebih besar dari cintamu pada kebenaran.
Aku tidak ingin melawanmu. Aku hanya ingin menulis apa adanya.
Bukankah Rasul pernah bersabda, ‘Tinta ulama lebih mulia daripada darah syuhada?’
Maka biarkan tintaku mengalir, meski mungkin meneteskan air matamu.”
Karno menutup map itu, menatap langit sore yang mulai jingga.
“Maafkan aku, Sri,” bisiknya lirih. “Aku tak pernah mengerti betapa sunyi perjuanganmu.”
Beberapa tahun berlalu.
Nama Sri semakin dikenal di kalangan akademisi. Tulisan-tulisannya tentang sejarah Nusantara, Islam Jawa, dan kolonialisme menjadi rujukan banyak penelitian. Mahasiswa dari berbagai negara datang ke Yogyakarta hanya untuk membaca karyanya.
Suatu siang, seorang dosen muda bernama Maryati mengunjungi rumah Karno. Ia datang membawa naskah tebal bertanda tangan penerbit internasional.
“Pak, kami akan menerbitkan karya lengkap Ibu Sri dalam versi bahasa Inggris. Judulnya ‘The Forgotten Queen of Java’.”
Karno menatap Maryati lama. “Kau muridnya?”
“Saya asisten beliau dulu, Pak. Ibu selalu berkata, sejarah harus ditulis tanpa takut pada siapa pun.”
Karno terdiam. Ia berjalan ke ruang tengah, menatap foto istrinya di dinding: Sri dengan toga hitam, wajahnya tegas tapi lembut.
Ia mengelus bingkai itu perlahan.
“Waktu hidup, aku selalu ingin menundukkanmu, Sri. Sekarang aku tahu, yang seharusnya tunduk itu aku—pada kebenaran yang kau perjuangkan.”
Maryati menunduk hormat. “Ibu pernah berkata, Bapak adalah inspirasinya menulis tentang cinta dan sejarah.”
Karno tersenyum samar. “Ia salah satu dari sedikit orang yang berani mencintai tanpa takut kehilangan dirinya sendiri.”
Malam itu, Karno menulis di buku hariannya—untuk pertama kali setelah sekian tahun:
“Aku mengerti kini.
Sejarah bukan sekadar nama dan tahun.
Ia adalah perjuangan untuk mengingat.
Dan Sri… engkau mengingatkan aku bahwa cinta sejati bukanlah menuntut kesamaan,
tapi keberanian untuk saling menanggung perbedaan.”
Ia menutup buku itu, menatap langit malam yang bersih.
Di luar, suara jangkrik terdengar bersahut-sahutan. Dalam hati, ia tahu—Sri belum benar-benar pergi. Ia hidup di antara kata-kata yang ditulisnya, di antara kalimat yang tak sempat selesai.
Dan di dalam dirinya, Karno akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini tak mampu ia pahami.
Tamat
*Ali Mustofa Trajutisna (AMT), tokoh sentral dan anggota dewan direktur pada periode pertama Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) tahun 1985 – 1989, dikenal sebagai sosok visioner dan penuh dedikasi.
Peran dan dedikasinya dalam mengembangkan serta menjalankan roda organisasi PPM sangatlah signifikan. Ia telah meninggalkan warisan yang tak ternilai dalam perjuangan PPM untuk beradaptasi dan tetap relevan di tengah perubahan peradaban yang cepat. Kontribusinya menjadikan beliau tokoh kunci dalam pondasi awal dan pertumbuhan PPM.