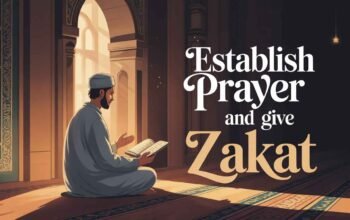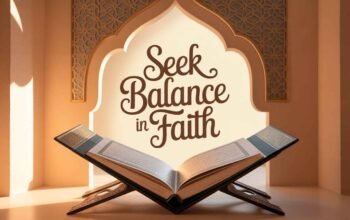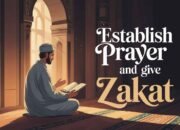Jakarta|PPMIndonesia.com– Setiap tahun umat Islam memasuki Ramadan dengan penuh semangat. Masjid ramai, tilawah meningkat, takjil dibagikan, sedekah mengalir. Namun satu pertanyaan mendasar jarang kita ajukan: puasa ini sesungguhnya untuk siapa?
Apakah ia sekadar kewajiban ritual formal? Ataukah ia dirancang untuk melahirkan perubahan sosial yang nyata?
Kajian Syahida—yakni membaca Al-Qur’an dengan Al-Qur’an (Qur’an bil Qur’an)—mengajak kita kembali kepada teks suci untuk menemukan jawabannya.
Tujuan Puasa: Takwa, Bukan Sekadar Lapar
Allah berfirman:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.”
(QS. Al-Baqarah: 183)
Ayat ini tegas: tujuan puasa adalah takwa.
Secara leksikal, takwa berasal dari akar kata وَقَى (waqa) yang berarti menjaga diri, melindungi, atau bersikap waspada. Maka takwa bukan sekadar kepatuhan formal, tetapi kesadaran preventif—kesadaran untuk tidak terjerumus dalam keburukan.
Jika puasa hanya menghasilkan lapar dan haus tanpa membentuk kewaspadaan moral, maka ruh ayat ini belum sepenuhnya terwujud.
Prinsip Kemudahan, Bukan Penyiksaan
Dalam rangkaian ayat yang sama, Allah menegaskan:
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu.”
(QS. Al-Baqarah: 185)
Puasa bukanlah bentuk penyiksaan diri. Ia bukan ritual asketisme ekstrem. Bahkan orang sakit dan musafir diberi keringanan.
Artinya, syariat puasa berdiri di atas prinsip kemaslahatan manusia. Maka jika pelaksanaan puasa kehilangan dimensi kemanusiaan dan empati, di situlah yang perlu kita koreksi.
Kritik Al-Qur’an terhadap Ritual Kosong
Al-Qur’an tidak segan mengkritik ibadah yang berhenti pada formalitas. Perhatikan Surah Al-Ma’un:
أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ
“Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang-orang yang shalat, yaitu mereka yang lalai dari shalatnya, yang berbuat riya dan enggan memberi bantuan.”
(QS. Al-Ma’un: 1–7)
Ayat ini mengguncang. Orang yang shalat pun bisa mendapat ancaman jika ibadahnya tidak melahirkan kepedulian sosial.
Apakah puasa berbeda? Tentu tidak.
Puasa dan Empati Sosial
Ramadan secara nyata membangkitkan empati. Ketika kita lapar, kita lebih mudah memahami rasa lapar orang lain. Ketika kita haus, kita lebih mudah merasakan derita mereka yang kekurangan.
Al-Qur’an mengaitkan takwa dengan keadilan:
اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
“Berlaku adillah, karena itu lebih dekat kepada takwa.”
(QS. Al-Ma’idah: 8)
Takwa bukan hanya kesalehan pribadi, tetapi juga kesalehan sosial. Maka puasa yang sejati harus berbuah pada keadilan, solidaritas, dan keberpihakan kepada yang lemah.
Bahkan dalam konteks fidyah, Allah memerintahkan:
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ
“Dan bagi orang-orang yang tidak mampu menjalankannya (puasa), wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin.”
(QS. Al-Baqarah: 184)
Sejak awal, puasa sudah dikaitkan dengan memberi makan orang miskin. Ini bukan tambahan budaya, tetapi bagian dari struktur ayat itu sendiri.
Kedekatan dengan Allah dan Kepedulian kepada Sesama
Rangkaian ayat puasa ditutup dengan firman Allah:
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat.”
(QS. Al-Baqarah: 186)
Kedekatan kepada Allah bukan hanya dicapai dengan menahan lapar, tetapi dengan hati yang lembut dan peduli.
Al-Qur’an kembali menegaskan:
لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ… وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ
“Bukanlah kebajikan itu menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan itu adalah beriman kepada Allah… dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, dan orang miskin.”
(QS. Al-Baqarah: 177)
Arah kiblat saja tidak cukup. Ritual saja tidak cukup. Puasa pun demikian—ia harus melahirkan keberpihakan.
Puasa untuk Siapa?
Puasa memang kewajiban individu. Tetapi tujuannya melampaui individu. Ia membentuk karakter sosial.
Puasa untuk siapa?
Untuk diri kita—agar menjadi pribadi yang waspada dan sadar.
Untuk masyarakat—agar lahir solidaritas dan keadilan.
Untuk Allah—sebagai bentuk penghambaan yang tulus.
Jika setelah Ramadan kita kembali abai terhadap tetangga yang kesulitan, kembali keras terhadap yang lemah, kembali kikir terhadap yang miskin, maka mungkin puasa kita masih berhenti pada ritual formal.
Namun jika puasa menjadikan kita lebih peka, lebih adil, lebih peduli—maka itulah puasa yang hidup.
Ramadan bukan sekadar kalender ibadah. Ia adalah proyek pembentukan kesadaran sosial.
Dan mungkin di situlah jawaban atas pertanyaan itu:
Puasa bukan hanya untuk kita, tetapi untuk menghadirkan kemaslahatan bagi sesama. (syahida)