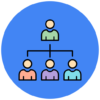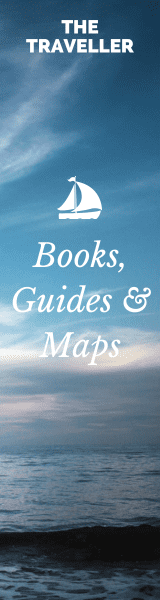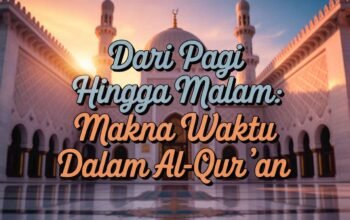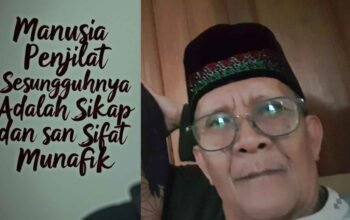ppmindonesia.com. Jakarta – Polemik sertifikat tanah di wilayah perairan, seperti yang terjadi pada kasus pagar laut di Tangerang dan Sidoarjo, memicu pertanyaan mendasar mengenai eksistensi hak atas tanah di wilayah tersebut. Secara yuridis, apakah mungkin seseorang atau badan hukum memiliki hak atas tanah di perairan pesisir? Bagaimana praktiknya di lapangan?
Landasan Yuridis Hak Atas Tanah di Perairan
Guru Besar Hukum Agraria Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Maria Suwardjono, menjelaskan bahwa hak atas tanah di wilayah perairan bukanlah hal yang baru. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
“Dalam pasal 1 UUPA sudah membuka peluang itu,” kata Maria. Pasal 1 ayat (4) UUPA menyebutkan bahwa pengertian tanah meliputi daratan yang posisinya di bawah air. Artinya, baik perairan pesisir maupun danau atau sungai, masuk dalam definisi tanah atau lahan.
Namun, hak atas tanah di perairan tidak dapat dipisahkan dari peraturan perundang-undangan lain, seperti Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Jika yang ingin dimanfaatkan adalah kolom airnya, maka perizinannya ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Praktik Lapangan: Masyarakat Adat dan Pemanfaatan Pesisir
Dalam praktiknya, hak atas tanah di perairan telah lama dimiliki oleh masyarakat adat yang tinggal di wilayah pesisir. Contohnya adalah Suku Bajo yang memiliki tradisi membangun rumah di atas air.
“Banyak sekali suku-suku asli yang rumahnya terapung, termasuk Suku Laut dan Suku Barok di Kepulauan Riau, atau HGB untuk suku Kampung Laut yang hidup di perairan Batam. Mereka punya hak atas lahan yang ditempatinya. Jadi, hak lahan di perairan pesisir itu memang bukan hal baru,” terang Maria.
Selain masyarakat adat, hak atas tanah di perairan juga diberikan kepada pihak lain, seperti pengembang yang melakukan reklamasi pantai.
Namun, pemberian hak ini harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan serta masyarakat sekitar.
Kontroversi dan Tantangan
Pemberian hak atas tanah di perairan seringkali menimbulkan kontroversi. Kasus pagar laut di Tangerang dan Sidoarjo menjadi contohnya. Masyarakat khawatir bahwa pembangunan di wilayah pesisir akan merusak lingkungan dan menghilangkan mata pencaharian mereka.
“Pesisir Tangerang termasuk kawasan abrasi luar biasa dahsyat. Dari total panjang pantai 745 kilometer, sebesar 44 persen menghilang ditelan abrasi,” ujar Maria.
Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang jelas dan komprehensif terkait hak atas tanah di perairan. Kebijakan ini harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan lingkungan, serta mengakomodasi hak-hak masyarakat adat dan masyarakat pesisir.(acank)
Referensi:
Referensi:
https://www.viva.co.id
https://news.republika.co.id
https://www.inilah.com
www.inilah.com