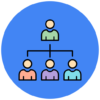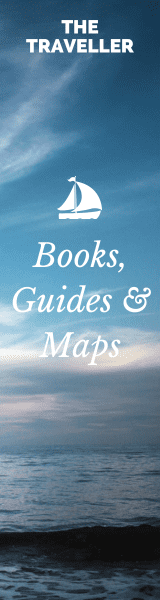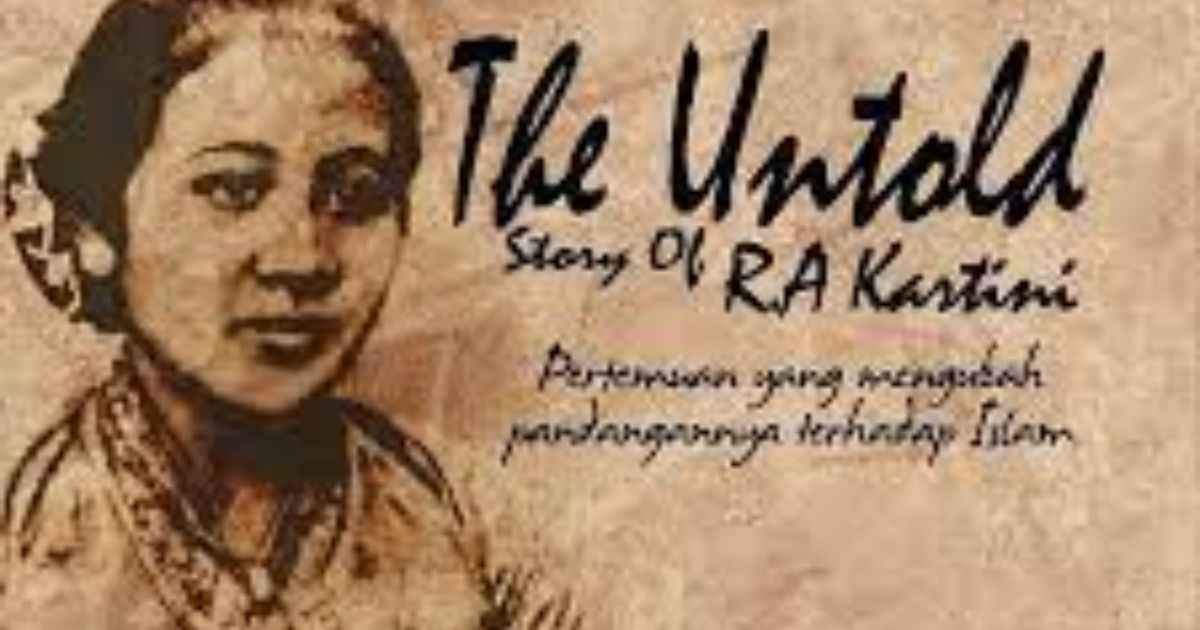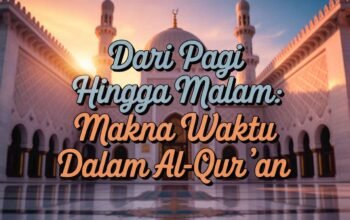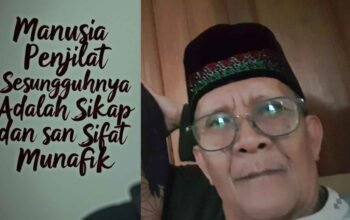ppmindonesia.com.Jakarta – Raden Ajeng Kartini kerap dijadikan simbol emansipasi perempuan dan bahkan diidentikkan sebagai ikon feminisme Indonesia. Namun, seiring berkembangnya wacana global, istilah feminisme kerap membawa muatan ideologis tertentu yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai spiritual, budaya lokal, dan ajaran Islam.
Dalam konteks ini, penting untuk membaca ulang perjuangan Kartini bukan semata-mata dalam kerangka feminisme Barat, tetapi dalam bingkai Islam yang memuliakan manusia secara utuh—baik laki-laki maupun perempuan.
Kartini lahir dan tumbuh dalam lingkungan priyayi Jawa yang kuat dipengaruhi sistem feodal dan kolonial. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana perempuan dipingit, dijauhkan dari pendidikan, dan dibatasi dalam ruang geraknya.
Namun yang menarik, kegelisahan Kartini terhadap kondisi kaumnya tidak serta-merta membuatnya menolak tradisi atau agama. Ia justru melakukan refleksi mendalam, mencari titik temu antara keadilan, budaya, dan spiritualitas.
Surat-surat Kartini, khususnya yang ditulis kepada sahabat-sahabatnya di Belanda, menjadi saksi betapa ia bergumul dengan banyak pertanyaan: tentang hak perempuan, keadilan sosial, pendidikan, dan makna keberagamaan.
Dalam salah satu suratnya, Kartini mengungkapkan kekaguman mendalam terhadap Al-Qur’an yang diterjemahkan oleh Kiai Sholeh Darat ke dalam bahasa Jawa. Ia menulis,
“Selama ini kami hanya disuruh mengaji tanpa tahu artinya. Baru sekarang saya merasa disinari oleh cahaya.” Kalimat ini menandai pentingnya pengetahuan dalam keberagamaan, dan bagaimana Kartini menemukan makna Islam sebagai agama yang membebaskan.
Pembacaan seperti ini membedakan perjuangan Kartini dari feminisme sekuler yang kerap berangkat dari penolakan terhadap agama dan norma sosial tradisional.
Kartini tidak mengajak perempuan untuk melawan kodratnya atau melepaskan diri dari peran domestik semata, melainkan untuk menjadi manusia merdeka—yang berpikir, terdidik, dan bermartabat di hadapan Tuhan dan sesama. Dalam Islam, perempuan memiliki kedudukan mulia sebagai ummu madrasah (ibu sebagai sekolah pertama), sebagai penjaga nilai, dan mitra sejajar dalam membangun masyarakat yang adil.
Islam tidak melihat perempuan sebagai subordinat laki-laki. Sebaliknya, Al-Qur’an menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari satu nafs (jiwa) yang sama, memiliki tanggung jawab moral yang sama, serta mendapat pahala dan ganjaran yang sama di sisi Allah atas amal perbuatannya.
Perspektif inilah yang tampaknya disadari Kartini, terutama dalam tahap akhir hidupnya, ketika ia semakin mendekatkan diri kepada nilai-nilai Islam yang inklusif dan pembebas.
Sayangnya, dalam arus modern, perjuangan Kartini seringkali dipersempit dalam narasi feminisme liberal, yang fokus pada kebebasan individual dan kesetaraan struktural semata, tanpa menyentuh akar spiritual dan dimensi transendennya.
Dalam narasi semacam ini, Kartini dikaburkan dari konteks budaya dan keagamaannya sendiri. Padahal, Kartini adalah perempuan Jawa-Muslim yang berpikir progresif tanpa tercerabut dari akarnya.
Membaca ulang Kartini dalam bingkai Islam bukan berarti mengabaikan keberaniannya, melainkan menempatkannya secara lebih utuh. Ia adalah sosok yang memperjuangkan keadilan dan kesetaraan dalam kerangka nilai yang luhur—bukan semata hak, tetapi juga tanggung jawab. Bukan sekadar kebebasan, tetapi juga kesadaran dan pengabdian.
Dengan demikian, Hari Kartini seharusnya tidak menjadi momen untuk mengimpor wacana feminisme luar, melainkan ruang refleksi untuk menggali nilai-nilai emansipasi yang berakar dari spiritualitas, kebudayaan, dan peradaban kita sendiri.
Kartini bukan sekadar pejuang perempuan, ia adalah sosok pencari kebenaran yang menemukan Islam sebagai jalan pembebasan. Dan di sinilah letak kekuatannya—bukan hanya sebagai ikon, tetapi sebagai inspirasi transformatif lintas zaman. (acank)