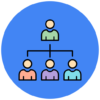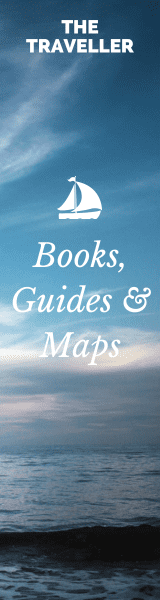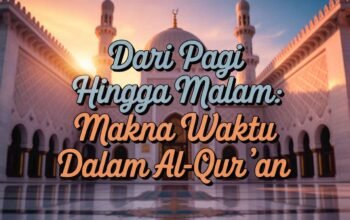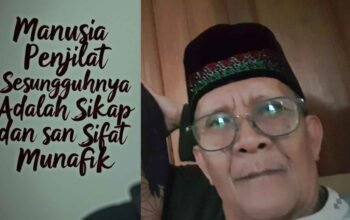ppmindonesia.com.Jakarta – Di pojok ruang perpustakaan sekolah yang hening, rak-rak buku berdiri kaku, menyimpan deretan ilmu yang kini seakan kehilangan peminatnya. Di sisi lain, di luar sana, sekelompok remaja duduk bersila saling berdampingan, namun mata mereka terpaku pada layar masing-masing.
Jempol-jempol mereka menari lincah, bergulir dari satu video singkat ke unggahan berikutnya. Inilah potret keseharian generasi milenial dan Gen Z—generasi yang lahir dan tumbuh dalam pelukan teknologi, namun perlahan menjauh dari budaya membaca.
Fenomena ini bukan sekadar anekdot. Data UNESCO mencatat bahwa tingkat minat baca masyarakat Indonesia berada pada angka yang memprihatinkan, yakni hanya 0,001.
Artinya, dari seribu orang, hanya satu yang benar-benar memiliki minat baca yang tinggi. Sebuah ironi di tengah klaim “era informasi” yang katanya menjadikan pengetahuan sebagai komoditas utama.
Menurut Dr. Atika Rahmawati, pakar literasi dari Universitas Negeri Yogyakarta, menurunnya minat baca di kalangan remaja tidak terjadi secara tiba-tiba.
“Kita sedang menyaksikan pergeseran budaya konsumsi informasi. Remaja lebih memilih konten yang cepat, visual, dan instan. Sementara buku, sebagai media baca tradisional, menuntut konsentrasi dan ketekunan—dua hal yang makin langka,” jelasnya.
Media sosial, game daring, dan platform video pendek seperti TikTok atau Instagram Reels menyajikan informasi dalam bentuk kilat dan menyenangkan.
Sayangnya, keasyikan ini menciptakan efek jangka panjang: rentang perhatian yang makin pendek, berkurangnya kemampuan memahami teks panjang, serta penurunan kemampuan berpikir kritis.
Buku yang menawarkan narasi panjang dan mendalam akhirnya kalah pamor. Dalam banyak kasus, keberadaan buku fisik di sekolah atau perpustakaan hanya menjadi hiasan yang berdebu.
Padahal, membaca bukan sekadar kegiatan akademik. Ini adalah pintu masuk untuk memahami dunia, memperluas empati, dan mempertajam logika.
Membaca juga menjadi fondasi dalam menumbuhkan pemikiran mandiri dan orisinal, sesuatu yang sangat dibutuhkan di tengah tsunami informasi dan disinformasi saat ini.
Menurut Psikolog Pendidikan, Dr. Syaiful Nursalim, membaca adalah aktivitas mental kompleks yang melatih otak untuk menyusun, menghubungkan, dan menalar.
“Ketika remaja tidak terbiasa membaca buku, maka mereka akan kesulitan menyusun argumen, mempertanyakan informasi, atau menilai sesuatu secara objektif,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa keterampilan literasi juga berkaitan erat dengan kesehatan mental, karena membaca menyediakan ruang kontemplasi dan pelarian dari tekanan sosial yang hadir di media digital.
Namun, semua belum terlambat. Di sejumlah daerah, komunitas literasi, taman baca masyarakat, bahkan sekolah-sekolah berbasis literasi mulai tumbuh kembali.
Mereka mencoba menghidupkan kembali gairah membaca lewat pendekatan baru: membaca tematik, diskusi buku, storytelling interaktif, hingga mengintegrasikan teknologi dengan literasi. Buku audio, e-book, dan platform membaca digital seperti iPusnas menjadi jembatan bagi generasi yang tak bisa lepas dari layar.
Dukungan keluarga juga sangat vital. “Anak yang tumbuh dalam lingkungan yang melihat orang tuanya membaca akan lebih mungkin meniru kebiasaan itu,” ujar Nurul Lestari, relawan literasi di Pustaka Kampung Impian.
Ia menekankan bahwa membaca harus diposisikan sebagai bagian dari gaya hidup, bukan sekadar tugas sekolah.
Gadget boleh menang dalam hal kecepatan dan daya tarik visual, namun buku tak seharusnya dilupakan. Karena dalam setiap lembar buku, tersimpan kekuatan untuk membentuk karakter, memperluas cakrawala, dan menumbuhkan bangsa yang kritis dan bijak. Kini saatnya menyandingkan teknologi dan literasi, bukan membiarkan yang satu menyingkirkan yang lain.(acank)