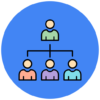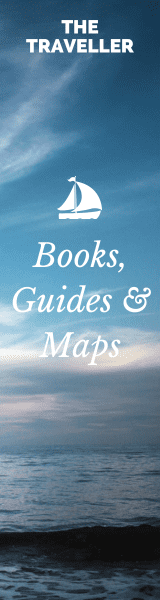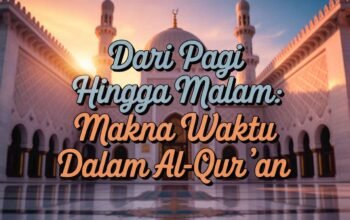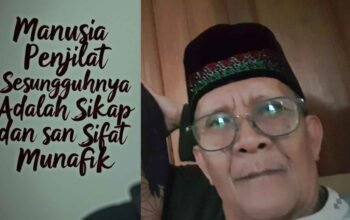Jejak Sejarah Pusat Peranserta Masyarakat (PPM)
ppmindonesia.com.Bekasi – Dalam sejarah panjang gerakan kemasyarakatan di Indonesia, nama Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) mungkin tak setenar partai politik atau lembaga negara. Namun, di balik layar reformasi sosial dan dakwah berbasis aksi nyata, lembaga ini memainkan peran penting—sebagai penjaga bara ketika ruang gerak rakyat dicekik oleh kebijakan kekuasaan.
Awal 1980-an menjadi titik balik. Kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK) dikeluarkan pemerintah untuk meredam aktivisme mahasiswa. Ruang politik dibekukan, mimbar kampus dibungkam. Namun seperti hukum sejarah, tekanan justru melahirkan inovasi. Dalam keheningan paksa itu, muncul kesadaran baru: bahwa perubahan tak melulu harus berteriak. Ia bisa hadir melalui kerja-kerja senyap yang menyentuh akar kehidupan rakyat.
Tahun 1982, sejumlah tokoh muda—di antaranya Adi Sasono (Lembaga Studi Pembangunan), Dawam Rahardjo (LP3ES), serta aktivis seperti Ali Mustofa Trajutrisna, Ki Suratno Hayuningrat, dan Seowarsono—menggelar lokakarya gerakan Dakwah Bil Hal di Malang. Konsepnya sederhana namun revolusioner: menyampaikan pesan-pesan Islam melalui praktik nyata di bidang ekonomi, sosial, dan budaya.
Gerakan itu menyebar cepat. Di Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Solo, hingga Bali dan Lombok, tumbuh komunitas-komunitas pemberdayaan dengan berbagai nama: Yayasan Ummu Salamah, Bina Karya, Kumbo Karno Institute, LPTP, Yayasan Fajar Jua, dan lainnya. Di tangan mereka, dakwah menjadi alat pemberdayaan: memajukan petani, mendampingi pemulung, hingga menghidupkan ekonomi lokal.
Dalam ingatan Pupun Purnama, salah satu presidium nasional PPM, semangat itu makin membuncah menjelang pergantian abad ke-15 Hijriyah. Sebuah proyek dakwah pembangunan bahkan dirancang bersama Departemen Agama dan Rabithah Alam Islami, menjangkau wilayah-wilayah yang saat itu rawan kristenisasi dan disorientasi sosial.
Pada tahun 1985, lebih dari 400 aktivis dan utusan lembaga berkumpul dalam Konvensi Dakwah Pembangunan. Mereka sepakat melebur dalam satu wadah: Pusat Pengembangan Masyarakat yang kemudian dikenal sebagai Pusat Peranserta Masyarakat (PPM). Direktorium pertama terdiri dari empat tokoh utama: Adi Sasono, Habib Chirzin, Ali Mustofa Trajutrisna, dan Heri Yuswantoh.
Tiga tahun berselang, pada Munas PPM 1988 di Bantul, format kepemimpinan berubah menjadi Presidium. Sosok seperti Hadi Mulya, Parito, Suratno, Suharyadi, dan Mursalin Dahlan menjadi ujung tombak.
Di bawah struktur ini, lahirlah berbagai program inovatif. Salah satunya adalah PGK (Pedagang Grosir Keliling)—gerakan ekonomi kerakyatan berbasis komunitas pedagang kecil yang dimodali lewat CSR BUMN, kala itu mencapai Rp350 juta. Ada pula geliat budaya melalui festival teater SMA, dan pendirian pesantren kejuruan di berbagai daerah, sebagian besar diinisiasi melalui kerja sama informal dengan ICMI.
Namun PPM bukan tanpa dinamika. Dalam beberapa periode nasional, kepemimpinan silih berganti. Nama-nama seperti Jumhur Hidayat, Farid Fathoni, Eko Suryono, Anas Hidayat, dan Nurhasan Ashari tercatat dalam sejarah gerakan. Pupun Purnama sendiri sempat menjadi Sekretaris Jenderal dan kemudian presidium pengganti antar waktu.
Kini, sebagian pendiri telah wafat. “Mereka sedang mengikuti konvensi di alam baka,” ujar Pupun dengan nada lirih, merujuk pada Adi Sasono, Habib Chirzin, dan Yoeswanto. Namun semangat mereka, katanya, tetap hidup dalam tubuh para kader dan komunitas yang masih bergerak di berbagai pelosok negeri.
PPM mungkin bukan organisasi yang sering muncul di halaman utama media. Namun dalam senyap, mereka telah membangun banyak hal yang menjadi fondasi perubahan sejati: membangkitkan kesadaran, menyatukan umat, dan menghidupkan kembali dakwah sebagai gerakan yang menyatu dengan denyut nadi rakyat.(acank)