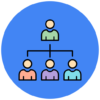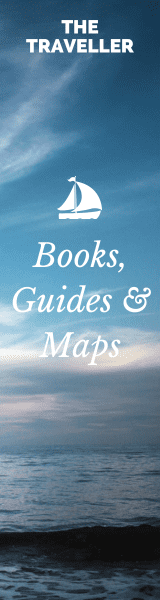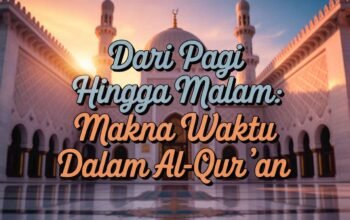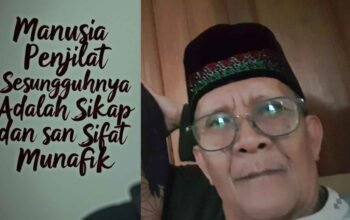ppmindonesia.com. Riau — Di sebuah pesantren di Riau, aroma tanah basah dan dedaunan busuk berpadu di udara. Di sudut halaman, para santri membolak-balik tumpukan kompos, memelihara cacing tanah, dan menyiangi kebun sayuran dengan cangkul di tangan.
Pemandangan ini bukan hanya cerita tentang pertanian, melainkan juga tentang mimpi besar: bagaimana lembaga pendidikan Islam mampu mandiri secara ekonomi tanpa harus ikut menyakiti bumi.
Ahad, 6 Juli 2025 lalu, Institut Pengembangan Masyarakat (IPAMA) menggelar workshop bertajuk “Mengelola Sampah dan Budidaya Cacing”, diikuti perwakilan dari tujuh pesantren se-Riau. Dipandu oleh Guntoro Soewarno, sebagai pemilik Ali Organic Farm (ALO FARM), penggiat pertanian organik, pelatihan itu memberi pelajaran sederhana tetapi mendalam: keberkahan bisa datang dari tanah yang dirawat dengan penuh tanggung jawab.
Modal Moral, Sosial, dan Alam
Pesantren selama ini dikenal sebagai pusat pendidikan agama yang hidup sederhana dan kadang bergantung pada donasi. Namun, tantangan zaman menuntut pesantren untuk juga mandiri secara ekonomi.
Masalahnya, banyak jalan menuju kemandirian justru merusak lingkungan. Padahal, seperti ditegaskan Guntoro di hadapan para peserta, “Menjadi mandiri itu baik, tetapi kalau caranya meracuni tanah, itu bukan hanya salah, tetapi juga melanggar amanah sebagai khalifah fil ardh.”
Para santri pun diajarkan mengelola sampah organik menjadi kompos, memelihara cacing untuk menyuburkan tanah, dan menanam di kebun pesantren tanpa pupuk kimia. Dari lahan kecil, hasilnya cukup mengejutkan: budidaya cacing di area 300 meter persegi saja bisa menghasilkan Rp8–15 juta per bulan.
“Cacing, kompos, dan kebun ini adalah modal pesantren yang murah, berkelanjutan, dan penuh keberkahan,” ujarnya.
Jejak Nabi dan Fikih Hijau
Pesantren organik sejatinya bukan konsep baru. Jauh sebelum istilah “organik” dipopulerkan, Nabi Muhammad SAW sudah memberi teladan: beliau melarang mencela tanah (HR Muslim), menganjurkan bercocok tanam meski kiamat sudah dekat (HR Bukhari), dan memanfaatkan kebun Madinah tanpa merusak ekosistem.
Dr. Fatmah Afifah, pakar ekoteologi UIN Jakarta, mengingatkan bahwa tanggung jawab manusia bukan hanya beribadah, tetapi juga menjaga bumi. “Kerusakan lingkungan hari ini adalah tanda bahwa kita lupa pada amanah itu,” katanya.
Data Kementerian Pertanian (2023) menunjukkan lebih dari 70 persen lahan pertanian Indonesia rusak akibat bahan kimia. KLHK (2022) mencatat lebih dari 3 juta ton pestisida mencemari air tanah tiap tahun. Pesantren organik menjadi alternatif nyata untuk keluar dari lingkaran perusakan lingkungan sambil menjaga kemandirian ekonomi.
Teladan dari Pesantren
Setelah workshop, para peserta membawa pulang tekad untuk mengubah wajah pesantren mereka. Sampah tidak lagi dibakar atau dibuang, melainkan dikelola. Lahan tidur disulap jadi kebun produktif. Para santri terlibat langsung mengolah tanah, menyemai bibit, dan memelihara cacing.
“Kami ingin pesantren jadi contoh. Tidak hanya bicara surga, tetapi juga merawat bumi,” ujar salah seorang peserta.
Pesantren memang punya posisi strategis: komunitas yang kuat, nilai-nilai yang luhur, dan kesadaran kolektif. Dari situ, mereka bisa memimpin jalan hijau bagi umat, menunjukkan bahwa ekonomi dan ekologi bisa berjalan seiring.
Bukan Sekadar Retorika
Krisis iklim dan lingkungan bukan hanya masalah global yang jauh dari kita. Ia sudah nyata di depan mata. Dan bagi umat Islam, menjaga bumi bukan sekadar opsi moral, melainkan juga perintah iman.
Pesantren organik adalah salah satu jawaban: kemandirian ekonomi yang tidak menambah luka bumi, melainkan menyembuhkannya.
Sebagaimana pesan seorang petani tua di Riau: “Tanah yang kita rawat hari ini akan menjadi doa bagi anak cucu kita kelak.”
Pesantren organik mengingatkan kita semua bahwa keberkahan bukan hanya datang dari doa yang dipanjatkan, tetapi juga dari cangkul yang menembus tanah, dari kompos yang menyuburkan bumi, dan dari tangan yang rela kotor demi merawat amanah-Nya.(emha)