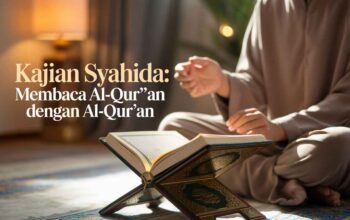ppmindonesia.com.Bogor — Setiap hari jutaan Muslim di seluruh dunia mengulang permohonan yang sama dalam shalat mereka: “Ihdinash shirathal mustaqim” — Tunjukkanlah kami jalan yang lurus.
Doa itu bukan sekadar penggalan surat Al-Fatihah, melainkan inti dari harapan spiritual umat Islam untuk mendapatkan bimbingan hidup dari Allah. Ironisnya, meskipun permohonan ini terus dipanjatkan, tak sedikit yang menganggap bahwa jalan lurus tersebut sulit ditemukan, bahkan digambarkan seperti rambut dibelah tujuh — begitu tipis, nyaris mustahil dikenali dan dijalani.
Pandangan ini mengundang keprihatinan. Bagi sebagian kalangan, istilah shirathal mustaqim seolah menjadi sesuatu yang abstrak dan tak terjangkau, padahal Al-Qur’an dengan jelas menyebutkan bahwa jalan lurus itu telah diwahyukan melalui Rasulullah.
Dalam QS Yasin ayat 2–4, Allah berfirman:
وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِۙ ٢اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَۙ ٣عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍۗ ٤
“Demi Al-Qur’an yang penuh hikmah, sesungguhnya engkau (Muhammad) termasuk dari para rasul, berada di atas jalan yang lurus.” Artinya, shirathal mustaqim bukanlah teka-teki gaib, melainkan jalan kenabian yang sudah ditunjukkan secara gamblang dalam Al-Qur’an.
Menolak Kejelasan Wahyu
Namun mengapa sebagian umat masih merasa jalan itu belum ditemukan? Ustadz Dr. Adian Husaini, cendekiawan Muslim dan Ketua Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia, menyoroti fenomena ini sebagai bentuk krisis pemahaman terhadap fungsi Al-Qur’an sebagai petunjuk. “Kita sering menjadikan Al-Qur’an hanya sebagai bacaan ritual, bukan sebagai pedoman hidup.
Padahal fungsi utamanya adalah sebagai petunjuk bagi manusia,” ujarnya
Senada dengan itu, Prof. Quraish Shihab dalam tafsirnya menyatakan bahwa jalan lurus dalam Al-Fatihah adalah jalan yang dibawa oleh para nabi dan rasul. “Dan jalan itu tidak samar, tidak pula sempit. Ia jelas, tegas, dan memandu manusia pada keselamatan,” tegasnya.
Sayangnya, dalam realitas sosial keagamaan, sebagian umat justru diajarkan bahwa memahami Al-Qur’an hanya bisa dilakukan oleh kalangan tertentu, atau bahwa jalan Allah terlalu rumit untuk dijangkau oleh orang awam. Ini memperparah kesenjangan antara ritual dan pemahaman. Surat Yasin, yang hampir setiap pekan dibacakan dalam majelis-majelis keagamaan, justru mengandung ayat-ayat penting tentang jalan lurus yang kerap terlewatkan maknanya.
QS 4:65: Tolok Ukur Keimanan
Kunci memahami jalan ini kembali ditegaskan dalam QS An-Nisa ayat 65:
فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ٦٥
“Mereka tidak akan beriman sebelum mereka menjadikan engkau (wahai Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusanmu dan mereka menerimanya dengan sepenuhnya.”
Ayat ini menjadi garis tegas bahwa keimanan tidak cukup dengan pengakuan lisan atau rutinitas ibadah. Keimanan sejati adalah ketundukan total kepada hukum dan keputusan Rasul, yang berarti kepada Al-Qur’an sebagai kitab yang beliau bawa. Dengan kata lain, jalan lurus bukan hanya permintaan dalam doa, tapi harus diwujudkan dalam cara hidup yang tunduk pada petunjuk wahyu.
Menyoal Tradisi Tanpa Pemahaman
Dalam berbagai kesempatan, baik di malam Jum’at, tahlilan, hingga pembacaan yasinan, umat Islam rutin membaca ayat-ayat tentang shirathal mustaqim, tetapi sering tanpa penghayatan makna. Menanggapi hal ini, KH. Afifuddin Muhajir, Pengasuh Ponpes Salafiyah Syafi’iyah Situbondo, menyampaikan, “Membaca Qur’an adalah ibadah, tapi memahami dan mengamalkannya adalah kewajiban yang lebih utama. Jangan sampai ibadah menjadi rutinitas kosong.”
Fenomena ini mencerminkan kritik Al-Qur’an dalam QS An-Nisa ayat 43 agar jangan mendekati shalat dalam keadaan “tidak sadar” atau tidak mengetahui apa yang dibaca. Shalat yang penuh permintaan tapi minim pemahaman bisa menjadi doa yang hampa.
Saatnya Menjadikan Qur’an Sebagai Hakim
Sudah waktunya umat Islam tidak hanya memohon jalan lurus, tetapi benar-benar menempuhnya. Jalan itu tidak lain adalah Al-Qur’an itu sendiri. Ia bukan jalan gelap, bukan pula teka-teki. Ia terang benderang — tetapi hanya bisa dilihat oleh mereka yang mau membuka mata hati, dan meletakkan ego, hawa nafsu, serta dogma turun-temurun di bawah cahaya wahyu.
Sebagaimana ditegaskan oleh Buya Hamka, “Al-Qur’an bukan kitab dongeng masa silam. Ia adalah obor yang menerangi jalan manusia menuju Allah.”
Maka, ketika jalan lurus dianggap seperti rambut dibelah tujuh, mungkin bukan karena jalannya yang kabur — tapi karena mata kita yang enggan terbuka.(husni fahro)
*Husni Fahro; peminat kajian Nasionalis Religius dan solidarits sosial, alumni IAIN Sumatera Utara tinggal di Bogor.