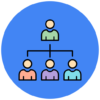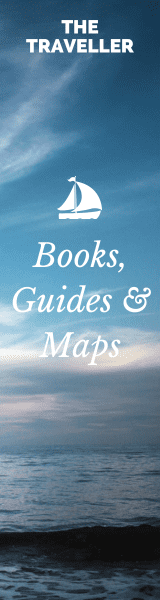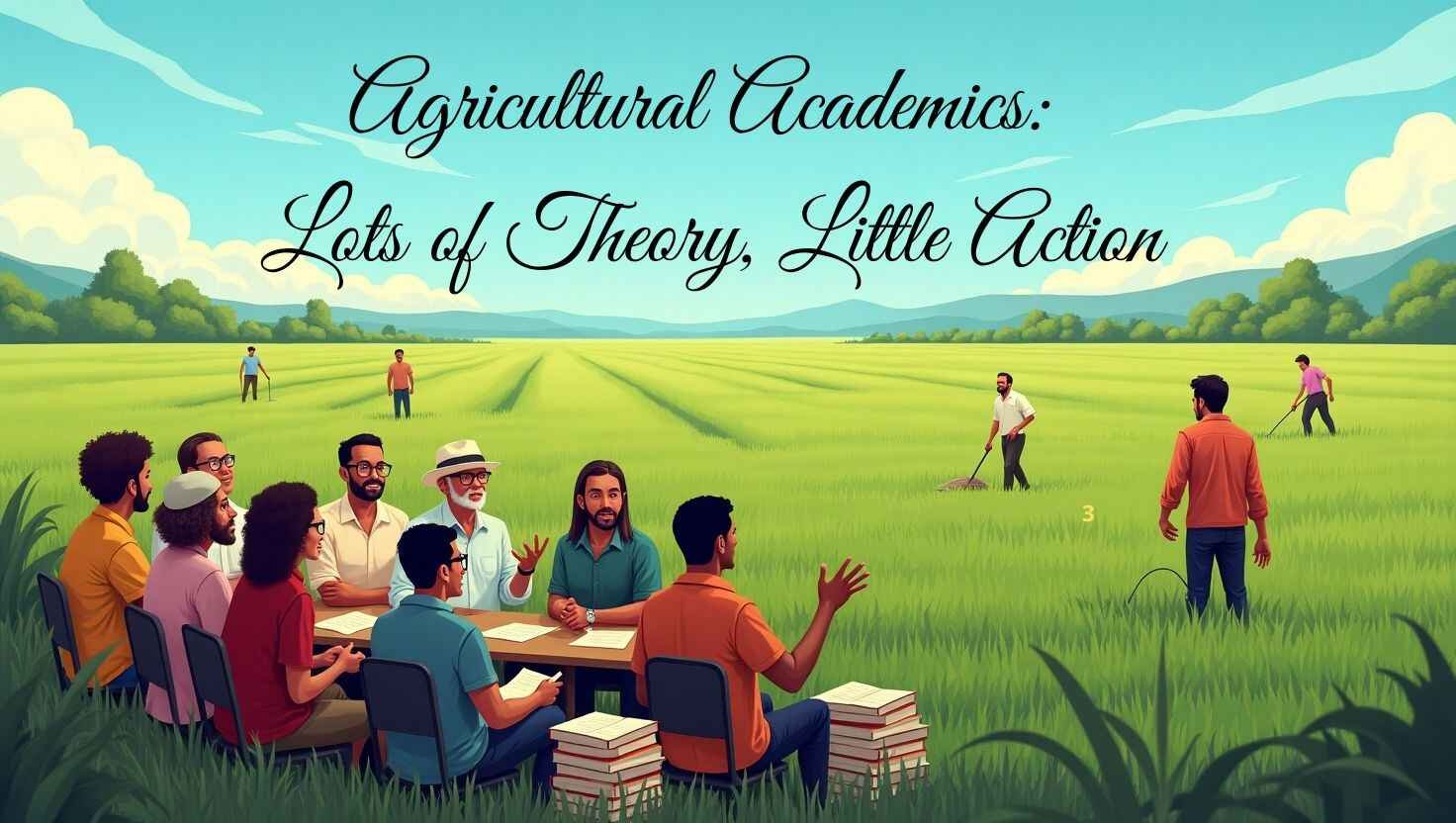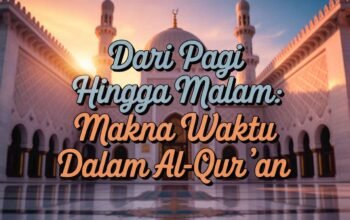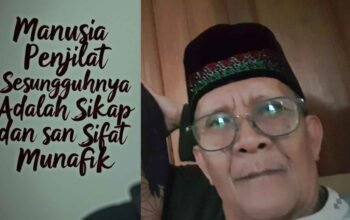pppmindonesia.com.Jakarta — Di tengah ancaman krisis pangan yang semakin nyata, suara para pakar pertanian seharusnya menjadi penggerak utama perubahan. Tapi kenyataannya, para akademisi dan lembaga pendidikan pertanian di Tanah Air cenderung diam dan lebih terjebak dalam dunia teori ketimbang aksi nyata di lapangan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar: mengapa para profesor pertanian yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan ketahanan pangan justru memilih jalan diam?
Institut Pertanian dan Paradigma yang Melenceng
Salah satu contoh nyata adalah Institut Pertanian Bogor (IPB), yang dikenal sebagai institusi pendidikan pertanian terbaik di Indonesia. Sayangnya, mayoritas lulusan IPB tidak menapakkan kaki mereka di sawah, melainkan berkiprah di kantor bank, perusahaan, atau lembaga birokrasi. Bahkan, menurut data tak resmi, lebih dari 90 persen lulusan IPB memilih jalur non-pertanian. Ironisnya, semangat transformasi sektor pangan seolah terkubur di balik angka-angka keuangan dan pengelolaan administrasi.
Akademik sebagai Paradigma Baru
Permasalahan utama terletak pada paradigma pendidikan yang terlalu menumpuk di atas teori dan publikasi internasional. Banyak profesor pertanian lebih sibuk mengejar angka sitasi dan reputasi di jurnal bereputasi seperti Scopus ketimbang membangun program pertanian yang menyentuh kehidupan petani kecil. Sistem ini menciptakan disparitas pengetahuan yang elitis dan jauh dari kenyataan field. Akibatnya, ide-ide inovatif yang sebenarnya dapat membantu rakyat kecil sering tertahan di atas kertas.
Teori Tinggi, Masalah Nyata Tak Tersentuh
Beragam teori pertanian mutakhir, seperti pertanian presisi, agroforestry, atau pertanian regeneratif, berkembang pesat di ruang akademik. Tapi di lapangan, persoalan petani tetap sama: pupuk mahal, harga jual rendah, dan tekanan pasar global yang tidak bersahabat. Para akademisi lebih banyak menjadi pengamat dari menara gading, bukan pelaku langsung yang turun ke sawah dan menyalurkan inovasi nyata.
Petani dan Pendidikan: Sebuah Ironi
Lebih ironis lagi, lulusan pertanian justru sering meragukan keberuntungan bertani sendiri. Seolah tidak percaya bahwa bertani bisa menguntungkan, mereka lebih nyaman berkarya di kantor atau lembaga riset. Kegagalan ideologi ini terlihat dari minimnya penguatan perekat antara pendidikan dan praktik di lapangan. Kurikulum yang jauh dari tanah pun menjadi salah satu sebabnya: praktikum di lab, magang di bank atau birokrat, bukan di kebun dan kelompok tani.
Diskusi Reboan Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) dan Arah Baru
Dalam diskusi Reboan Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) Nasional yang dihadiri oleh Presidium dan Sekretaris Jenderal, penting ditekankan: saatnya melakukan revolusi pendidikan pertanian di Indonesia. Untuk membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan, perguruan tinggi harus mengubah paradigma dan memberi ruang nyata bagi mahasiswa untuk belajar langsung dari petani.
Beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain:
- Wajibkan magang lapang di desa, bukan di kantor pemerintahan.
- Berikan insentif kepada dosen yang aktif mendampingi petani dan mengaplikasikan pengetahuan langsung di lapangan.
- Dirikan koperasi tani berbasis kampus sebagai laboratorium sosial dan ekonomi rakyat.
- Dorong mahasiswa menjadi agropreneur, bukan semata menjadi aparatur sipil negara atau analis.
Membangun ketahanan pangan bukan hanya tugas pemerintah atau petani tradisional, tetapi juga tanggung jawab akademisi dan institusi pendidikan. Jika teori terus berkutat di ruang seminar dan jurnal, maka jawaban atas krisis pangan akan semakin jauh dari kenyataan.
Kini saatnya beraksi, turun ke sawah, memperkuat petani, dan menciptakan inovasi nyata untuk negeri.(acank)