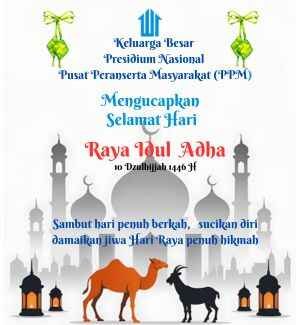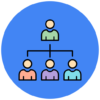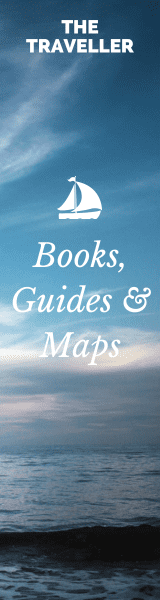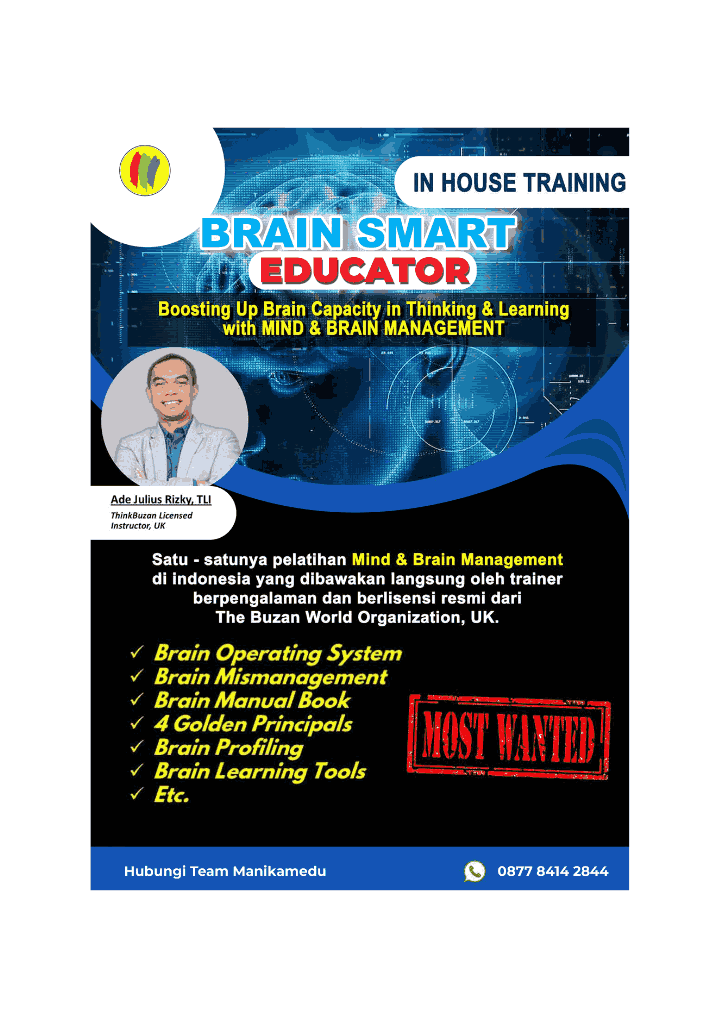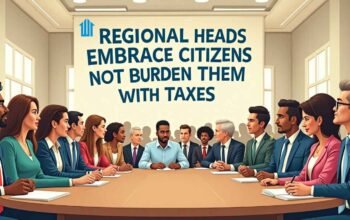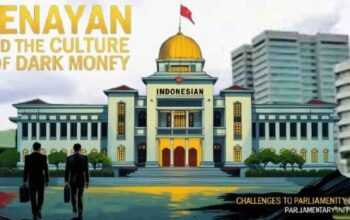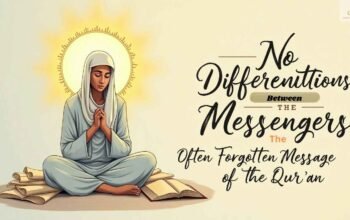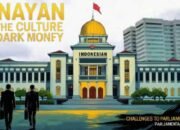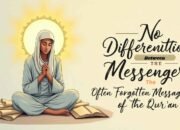ppmindonesia.com.Jakarta – Kebijakan membuka kembali rekening masyarakat yang dinyatakan “dormant” oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mungkin terkesan sebagai langkah korektif.
Namun, publik jangan buru-buru menyambutnya dengan pujian. Sebab kenyataannya, pelonggaran ini bukanlah bukti bahwa negara memperbaiki diri—melainkan bentuk pengakuan diam-diam atas kekacauan logika kebijakan yang pernah (dan mungkin masih) dijalankan atas nama “intelijen keuangan”.
Selama ini, kita hidup dalam sebuah sistem pengawasan yang menjadikan diam sebagai kejahatan, tabungan sebagai kecurigaan, dan kehati-hatian finansial sebagai penyamaran kriminal.
Negara memperlakukan rekening tak aktif sebagai potensi pencucian uang atau tindak pidana, tanpa pernah bertanya apakah rekening itu adalah milik seseorang yang sedang menyimpan dana untuk operasi, biaya kuliah anaknya lima tahun lagi, atau sekadar dana darurat untuk masa depan yang tak pasti.
PPATK tampaknya lupa bahwa tak semua orang hidup dalam irama transaksi harian. Sebagian besar rakyat justru menabung dengan cara yang paling wajar: menyimpan uang dan membiarkannya diam sampai dibutuhkan. Tetapi dalam logika PPATK, keheningan finansial justru adalah musuh.
Alih-alih menjalankan prinsip kehati-hatian, PPATK justru menjebak diri dalam paranoia institusional. Dengan dalih memberantas judi online, mereka menyebar jaring yang terlalu besar dan terlalu kasar: membekukan jutaan rekening tanpa bukti, tanpa prosedur hukum, tanpa klarifikasi, dan tanpa ruang pembelaan. Hingga Mei 2025, tercatat sebanyak 31 juta rekening telah diblokir—dengan nilai mencapai Rp 6 triliun—atas dasar kriteria yang absurd: terlalu lama tidak bergerak.
Ironisnya, dari total itu, lebih dari 10 juta adalah rekening penerima bantuan sosial, dengan dana mengendap Rp 2,1 triliun. Bahkan 2.000 lebih adalah rekening milik instansi pemerintah dan bendahara pengeluaran. Tapi semua itu dikesampingkan oleh satu logika besar: diam berarti jahat, pasif berarti kriminal.
Negara Hukum atau Negara Curiga?
Pemblokiran ini tidak hanya ngawur secara ekonomi, tetapi juga cacat secara hukum. Dalam negara hukum, asas presumption of innocence seharusnya menjadi fondasi—bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya. Namun PPATK justru bekerja berdasarkan presumption of suspicion: curiga dulu, bekukan dulu, cari buktinya nanti.
Rekening milik pelajar, petani, pengemudi ojek online, ibu rumah tangga, hingga pensiunan ikut dibekukan. Tak ada ruang klarifikasi. Tak ada peringatan. Tak ada pembuktian. Padahal PPATK bukanlah lembaga penegak hukum.
Ia bukan polisi, bukan jaksa, apalagi hakim. Fungsinya adalah menganalisis dan melaporkan, bukan mengeksekusi. UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU pun dengan jelas membatasi kewenangannya.
Menurut ketentuan, PPATK hanya boleh meminta pemblokiran sementara kepada lembaga keuangan jika ada dugaan kuat keterlibatan tindak pidana. Itu pun maksimal 30 hari dan wajib ditindaklanjuti oleh aparat hukum. Tetapi dalam kasus ini, PPATK tidak hanya melampaui kewenangan, tapi juga melecehkan proses hukum itu sendiri.
Politik Kepatuhan yang Pincang
Di sisi lain, kita juga menyaksikan ketimpangan yang menyakitkan. Mengapa begitu mudah dan cepat PPATK memblokir rekening milik rakyat biasa, tetapi begitu lamban, ragu-ragu, bahkan tak bernyali ketika berhadapan dengan rekening milik pejabat, politisi, atau tokoh berpengaruh?
Ingat, pada 2024 PPATK melaporkan adanya transaksi mencurigakan senilai Rp 80,1 triliun yang melibatkan partai politik dan pejabat publik. Namun hingga kini, tak ada pemblokiran. Tak ada tindakan hukum. Tak ada transparansi. Yang ada hanyalah laporan yang dibiarkan menguap bersama kepentingan.
Inilah wajah ketidakadilan struktural yang tak bisa ditutup-tutupi. PPATK menjalankan “keberanian horizontal”—garang ke bawah, tumpul ke atas. Kepada rakyat kecil yang menyimpan uang secara diam-diam, PPATK bersikap represif. Tapi kepada elite yang memutar uang dalam senyap, PPATK hanya mengirim dokumen.
Dari FIU Menjadi Algojo Finansial?
Kekacauan ini sebenarnya telah lama diperingatkan dalam literatur internasional. Dalam bukunya Anti-Money Laundering: A Comparative and Critical Analysis (2016), Alhosani menyebut fenomena ini sebagai function creep—ketika lembaga intelijen keuangan (Financial Intelligence Unit/FIU) menyimpang dari peran analitik menjadi eksekutor.
Padahal, secara prinsip global, FIU tidak boleh memiliki wewenang pemblokiran langsung tanpa keterlibatan lembaga penegak hukum atau perintah pengadilan. Tetapi dalam kasus Indonesia, PPATK justru menjelma menjadi hakim, jaksa, dan algojo sekaligus. Ini bukan lagi kerja intelijen keuangan, ini adalah bentuk otoritarianisme finansial.
Saatnya Diperiksa
Maka tak cukup hanya membuka kembali rekening yang diblokir. Harus ada evaluasi menyeluruh. Harus ada pertanggungjawaban. Kepala PPATK harus dimintai keterangan. Seluruh proses pemblokiran massal harus diaudit. Kerja sama antara PPATK dan perbankan harus diperiksa.
Presiden pun tidak bisa bersembunyi. PPATK adalah lembaga yang berada langsung di bawah kendali Presiden. Jika pembekuan dilakukan tanpa sepengetahuan Kepala Negara, maka itu adalah kegagalan pengawasan. Jika dilakukan dengan sepengetahuan, maka itu adalah bentuk pelanggaran hukum yang disponsori negara.
Negara Harus Belajar Mendengar
Negara yang baik bukan negara yang curiga kepada warganya sendiri. Negara yang baik adalah negara yang tahu kapan harus tegas dan tahu kapan harus bijak. Dalam menghadapi kejahatan keuangan, presisi adalah kunci. Jangan menjadikan rakyat sebagai collateral damage dalam perang melawan kriminalitas yang tidak pernah diselesaikan di hulu.
Dalam sistem demokrasi, akuntabilitas bukan pilihan, melainkan kewajiban. Jika negara gagal membedakan antara kehati-hatian dan kriminalitas, maka rakyat hanya akan melihat pemerintah sebagai ancaman baru atas hak-hak dasar mereka. Dan jika itu terjadi, maka bukan keadilan yang ditegakkan—melainkan ketakutan yang dipelihara. (acank)