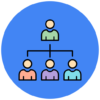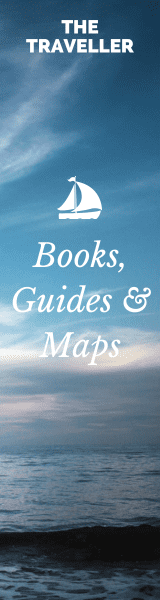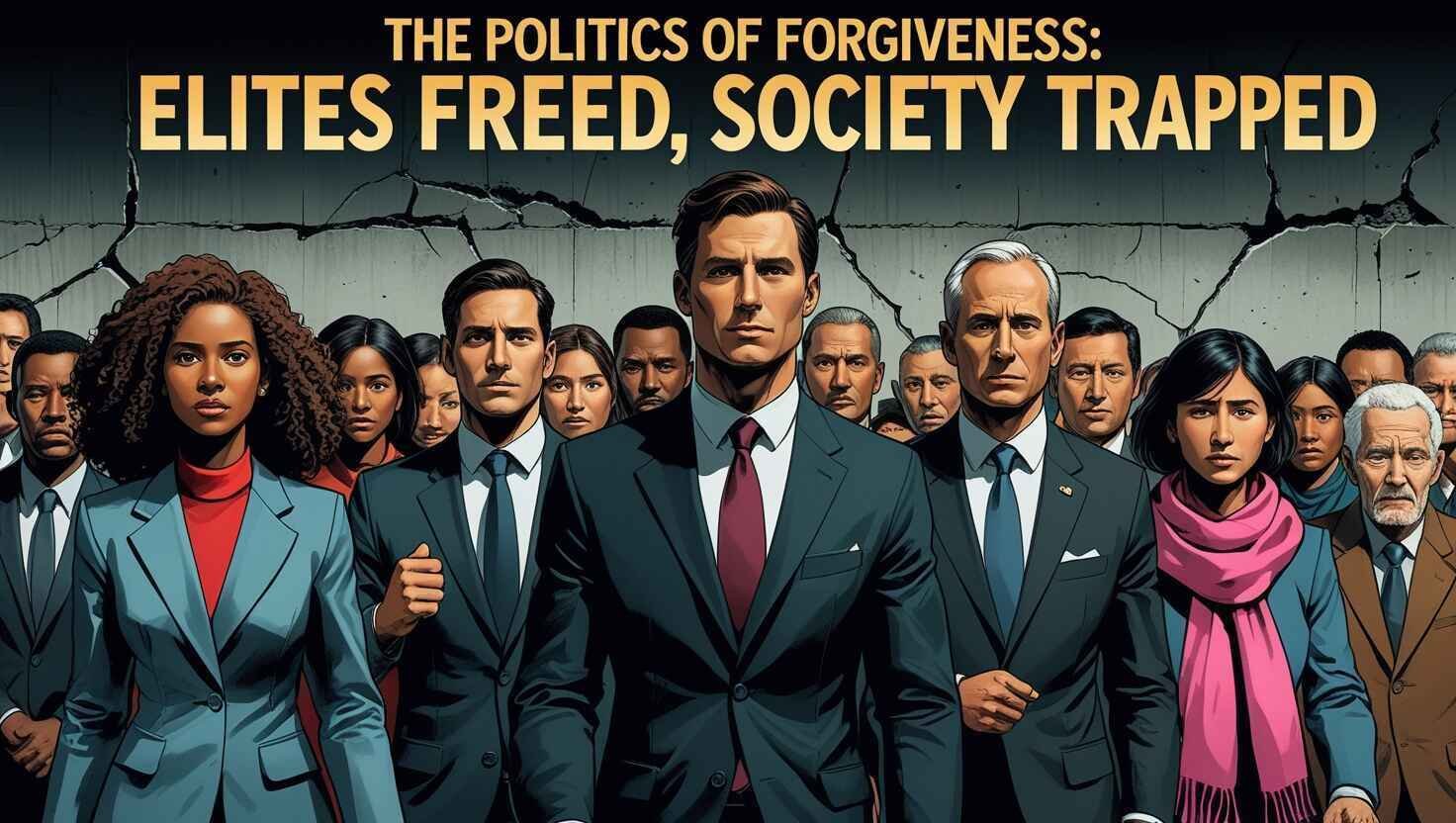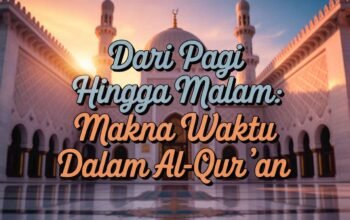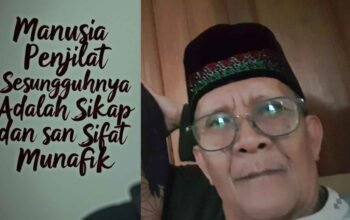ppmindonesia.com. Jakarta, Pemberian amnesti dan abolisi oleh Presiden Prabowo Subianto kembali menggema, memunculkan pertanyaan tajam dari masyarakat: siapa yang sebenarnya diuntungkan dari kebijakan pengampunan ini? Di tengah situasi ekonomi yang menekan dan kepercayaan publik terhadap hukum yang terus diuji, narasi “rekonsiliasi nasional” justru kian terasa sebagai politik selektif yang lebih menyasar elite daripada rakyat kebanyakan.
Bagi sebagian besar masyarakat, hukum tetaplah seperti jerat yang rumit. Mereka yang mempertahankan tanah, memperjuangkan upah layak, atau membela lingkungan sering berujung pada kriminalisasi. Namun, bagi elite politik dan ekonomi, jalur pengampunan terbuka lebar, diberi label “demi persatuan” atau “kestabilan nasional”.
Ketimpangan dalam Nama Pengampunan
“Yang dibebaskan adalah mereka yang punya akses ke kekuasaan, yang dibela adalah mereka yang punya posisi tawar politik,” ujar Dr. Bivitri Susanti, pengamat hukum tata negara. “Sementara masyarakat kecil yang menuntut hak hidupnya, terus terjebak dalam proses hukum yang tak berpihak.”
Sejak masa reformasi, pengampunan presiden memang menjadi alat strategis yang sah secara konstitusional. Pasal 14 UUD 1945 memberi kewenangan presiden untuk memberikan amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR. Namun, persoalannya bukan semata legalitas, melainkan keadilan substantif: mengapa amnesti begitu mudah untuk elite, tapi nyaris tak tersedia untuk rakyat kecil?
PPM: Keadilan Seharusnya Inklusif
Kritik tajam datang dari organisasi masyarakat sipil, Pusat Peranserta Masyarakat (PPM), yang menyoroti praktik pengampunan yang dianggap eksklusif dan elitis. “Apakah kita sedang menyaksikan pengampunan selektif—di mana yang diampuni adalah mereka yang punya kekuatan politik, sementara masyarakat yang berjuang demi keadilan struktural terus dipenjara?” tanya Anwar Hariyono Sekretaris Jenderal PPM Nasional
Menurutnya, jika benar Presiden hendak membuka babak baru rekonsiliasi nasional, maka seharusnya langkah itu menyentuh pula mereka yang selama ini dimarjinalkan oleh sistem hukum. “Ada petani, nelayan, jurnalis, dan aktivis yang dihukum karena memperjuangkan hak publik. Mereka juga berhak mendapat pengampunan—bahkan lebih berhak dari mereka yang menyalahgunakan kekuasaan,” tegas Anwar
Rakyat Terjebak, Elite Terlepas
Dalam beberapa kasus, seperti kriminalisasi terhadap pembela lingkungan di Kalimantan, atau proses hukum terhadap warga adat di Papua dan Maluku, masyarakat sipil merasa hukum berjalan tanpa keberpihakan. Di saat bersamaan, para elite yang diduga melakukan korupsi atau pelanggaran HAM memiliki peluang dimaafkan melalui mekanisme politik.
Prof. Syamsuddin Haris, peneliti senior di BRIN, menyebut kondisi ini sebagai bentuk ketimpangan struktural dalam demokrasi elektoral. “Kita menghadapi demokrasi yang prosedural, tapi tidak substantif. Di sinilah bahaya pengampunan politik yang tidak dibarengi dengan reformasi hukum,” ujarnya.
Menakar Legitimasi Moral
Jika pengampunan hanya menjadi alat kompromi politik, maka yang dikorbankan adalah kepercayaan publik terhadap negara hukum. Lebih buruk lagi, hal ini dapat menormalisasi impunitas di ruang politik.
Di tengah krisis kepercayaan dan tantangan ekonomi, masyarakat Indonesia berharap pemerintah tidak hanya bermain simbolik dengan rekonsiliasi. Mereka ingin melihat keadilan yang menyentuh akar, bukan hanya upaya menutupi konflik elite dengan kebijakan populis.
Menuju Rekonsiliasi yang Setara
Rekonsiliasi sejati bukan hanya memaafkan masa lalu, tapi juga membenahi ketimpangan yang selama ini dibiarkan. Jika negara ingin berdamai dengan sejarah, maka semua pihak—bukan hanya elite—harus diberikan ruang untuk dipulihkan.
Politik pengampunan yang adil bukan yang membuat elite terbebas dan masyarakat tetap terjebak. Tapi yang memberi harapan baru, bahwa hukum dapat berpihak pada yang lemah, dan kekuasaan dapat dirasakan sebagai pelindung, bukan sekadar alat tawar-menawar. (acank)