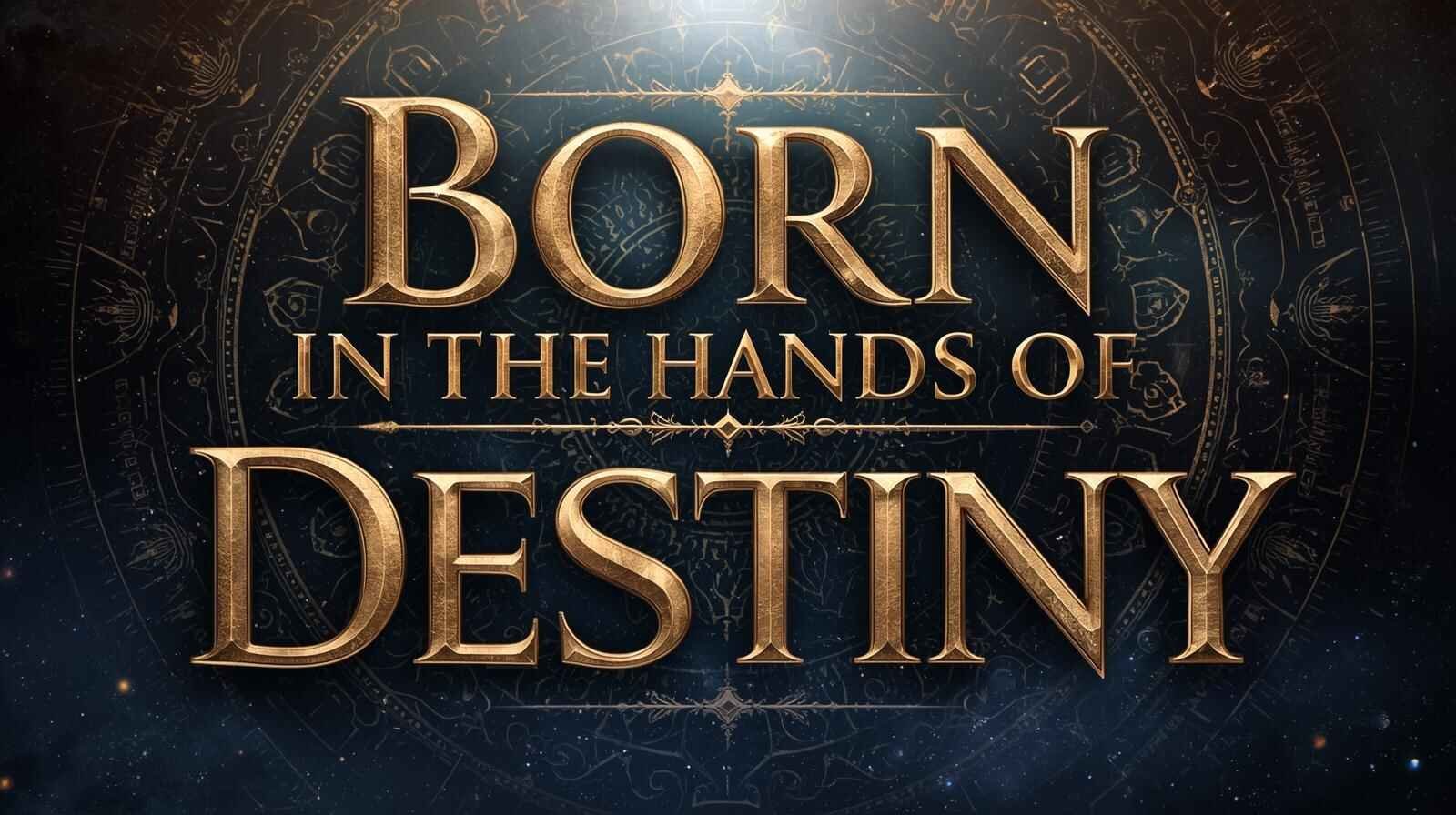“Lahir di Tangan Takdir”
Oleh: Dimas
Di sebuah desa kecil di kaki gunung yang berkabut setiap pagi, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Raka. Ia dilahirkan dalam keluarga sederhana yang taat beragama dan sangat bangga akan sukunya. Sejak kecil, Raka diajarkan bahwa sukunya paling luhur, bahasanya paling indah, dan agamanya paling benar. Ia percaya begitu saja, sebab siapa pula yang tidak percaya pada apa yang ditanamkan oleh ayah dan ibunya sejak pertama ia bisa bicara?
Namun, di sekolah, Raka bertemu dengan Lina, anak perempuan dari suku lain, beragama lain. Lina baik, pintar, dan suka menolong. Suatu hari, saat Raka menolong Lina yang terjatuh di halaman sekolah, teman-teman Raka menegur keras.
“Jangan terlalu dekat! Dia bukan dari kita.”
Kata-kata itu menancap di kepala Raka seperti paku dingin di pagi hari. Malamnya, ia bertanya kepada ibunya,
“Bu, kenapa Lina tidak boleh jadi teman saya? Padahal dia baik.”
Ibunya menjawab lembut tapi tegas,
“Karena mereka berbeda, Nak. Dunia ini harus dijaga supaya kita tidak bercampur dengan yang bukan golongan kita.”
Raka diam. Ia tidak mengerti. Ia masih kecil, tapi batinnya menolak. “Kalau Tuhan menciptakan semua manusia, kenapa harus dibatasi?” pikirnya. Tapi ia simpan pertanyaan itu, karena ia tahu pertanyaan seperti itu bisa membuat orang marah.
Tahun berganti. Raka tumbuh menjadi remaja. Ia mulai mengenal dunia lewat buku dan internet. Ia membaca tentang bagaimana di tempat lain, orang berdoa dengan cara berbeda, tapi tetap menyebut nama Tuhan. Ia membaca puisi Jalaluddin Rumi dan menangis di tengah malam. Dalam bait-bait itu, ia merasa menemukan sesuatu yang tidak pernah diajarkan: bahwa cinta jauh lebih luas dari agama, dan kasih sayang lebih dalam dari batas suku.
Suatu hari, ketika Raka beranjak dewasa, perang pecah di negerinya. Bukan karena kelaparan atau bencana, melainkan karena agama. Orang-orang yang dulunya bersalaman kini saling menghunus senjata. Rumah Lina terbakar. Ayahnya hilang. Dan Raka, yang kini bekerja sebagai relawan kemanusiaan, menyelamatkan siapa pun yang ditemuinya—tanpa menanyakan apa sukunya, apa agamanya.
Seorang prajurit dari kelompoknya menegur keras,
“Kenapa kamu tolong mereka? Mereka bukan seiman!”
Raka menjawab dengan wajah penuh debu dan mata basah,
“Kalau Tuhan menolong hanya yang seiman, lalu siapa yang menolong Tuhan saat manusia kehilangan kasih?”
Di tengah reruntuhan masjid dan gereja yang sama-sama terbakar, Raka menemukan Lina, terluka parah tapi masih bernapas. Ia menatapnya dan berbisik,
“Maaf, dunia orang dewasa terlalu bising untuk mendengar hati anak-anak yang dulu hanya ingin berteman.”
Malam itu, di bawah langit yang penuh asap, Raka berdoa—bukan dalam bahasa agamanya, tapi dalam bahasa kemanusiaan:
“Tuhan, kalau Engkau benar Maha Kuasa, jadikanlah kasih sebagai agama yang satu.”
Beberapa tahun kemudian, perang usai. Di tanah yang porak-poranda itu, Raka mendirikan sekolah perdamaian, tempat anak-anak dari berbagai keyakinan belajar bersama tanpa takut ditanya siapa Tuhan mereka. Di dinding sekolah itu tertulis satu kalimat:
“Kita semua lahir di tangan takdir, tapi kita bisa memilih untuk menjadi manusia.”
Dan sejak hari itu, Raka tidak lagi sibuk mencari siapa yang benar. Ia memilih untuk menjadi orang yang baik.