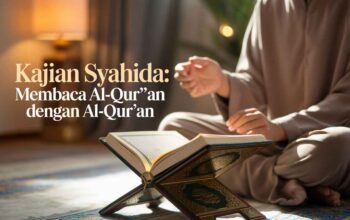ppmindonesia,com, Jakarta – Di tengah derasnya arus informasi dan opini di dunia maya, kita seolah hidup dalam zaman yang penuh percakapan, tetapi miskin dialog.
Semua orang berbicara, sedikit yang mendengar.
Semua ingin didengar, sedikit yang memahami.
Ruang publik digital, yang dulu diharapkan menjadi tempat pertukaran gagasan yang rasional, kini berubah menjadi arena pertarungan ego dan emosi.
Akal sehat tergantikan oleh sorak dan sindiran.
“Kita berbicara semakin banyak, tetapi saling memahami semakin sedikit.”
Ruang Publik yang Bising, Tapi Sepi Makna
Kita sering mengira kebebasan berpendapat berarti bebas berteriak tanpa batas.
Namun, kebebasan tanpa kemampuan berdialog hanya melahirkan kebisingan.
Di media sosial, setiap isu—dari kebijakan publik hingga perkara hukum—cepat berubah menjadi bahan olok-olok dan adu opini dangkal.
Tidak ada ruang untuk mendengar yang berbeda.
Kritik dituduh sebagai kebencian, perbedaan pandangan dianggap pengkhianatan.
Kita hidup dalam gelembung kebenaran masing-masing, di mana algoritma menampilkan hanya apa yang ingin kita dengar.
“Dialog membutuhkan keberanian untuk mendengar yang tidak kita setujui.”
Dari Rasionalitas ke Rivalitas
Ruang publik idealnya adalah tempat warga bertemu, berdiskusi, dan mencari kebenaran bersama.
Namun, kini ia telah berubah menjadi gelanggang kompetisi opini—siapa paling keras, dialah yang menang.
Argumentasi tergantikan oleh sarkasme, fakta kalah cepat dari sensasi.
Fenomena ini bukan hanya mencerminkan perubahan budaya komunikasi, tetapi juga menandakan krisis rasionalitas.
Kita lebih percaya pada potongan video daripada naskah keputusan resmi, lebih mudah tergerak oleh retorika ketimbang data.
Sosiolog Jürgen Habermas pernah membayangkan ruang publik sebagai arena rasional di mana warga berdialog secara setara untuk mencari kebenaran bersama.
Kini, bayangan itu tinggal idealisme akademik di tengah dunia digital yang sibuk mengejar engagement.
Politik Tanpa Substansi, Hukum Tanpa Wibawa
Ketika dialog mati, politik pun kehilangan arah.
Debat publik tentang kebijakan sering kali berujung pada serangan pribadi, bukan adu gagasan.
Pemimpin yang menampilkan empati dan kedalaman pemikiran justru kalah populer dari yang pandai bergaya di depan kamera.
Demikian pula hukum.
Setiap kali muncul putusan penting, masyarakat lebih sibuk mencari siapa yang diuntungkan, bukan apa yang ditegakkan.
Padahal, demokrasi yang sehat bertumpu pada dua hal: rasionalitas politik dan integritas hukum.
“Tanpa dialog, hukum kehilangan keadilan; politik kehilangan arah.”
Media Sosial dan Ilusi Keterlibatan
Media sosial memberi kesan bahwa semua orang terlibat dalam percakapan nasional.
Namun sering kali, yang terjadi hanyalah monolog berjamaah.
Kita tidak berdialog untuk memahami, melainkan untuk menang.
Kolom komentar menjadi arena debat tanpa kesimpulan, tempat setiap orang berlomba mengukuhkan pendapat sendiri.
Partisipasi berubah menjadi performa, kritik berubah menjadi konten.
Semua tampak sibuk “berpikir”, tapi sedikit yang benar-benar merenung.
“Ruang publik tanpa dialog adalah panggung, bukan forum.”
Menumbuhkan Kembali Tradisi Berpikir dan Berdialog
Menghidupkan kembali akal sehat publik adalah pekerjaan kebudayaan, bukan sekadar regulasi.
Ia memerlukan pendidikan yang menumbuhkan nalar kritis dan empati.
Anak muda perlu diajak berani berdebat dengan argumen, bukan dengan kemarahan.
Media juga memegang peran sentral.
Di tengah hiruk-pikuk informasi cepat, media profesional harus kembali menjadi jangkar kedalaman.
Mereka perlu menghadirkan ruang reflektif, bukan sekadar tempat adu kutipan.
Selain itu, pemimpin publik harus menampilkan keteladanan dialogis—mendengar kritik, merespons dengan data, dan tidak membungkam perbedaan.
Hanya dengan begitu, publik akan belajar bahwa berpikir berbeda bukan dosa, melainkan tanda hidupnya demokrasi.
Menjaga Akal Sehat Demokrasi
Demokrasi tanpa dialog hanyalah ritual suara, bukan perayaan akal sehat.
Kita membutuhkan ruang publik yang kembali rasional, inklusif, dan jujur.
Tempat di mana perbedaan bukan ancaman, melainkan sumber pemahaman baru.
Mungkin inilah saatnya kita berhenti berdebat untuk menang, dan mulai berbicara untuk mengerti.
Sebab, bangsa yang besar bukanlah bangsa yang paling ramai berbicara—melainkan yang paling tenang mendengarkan.
“Dialog adalah jantung demokrasi; ketika ia berhenti berdetak, yang tersisa hanyalah kebisingan.”