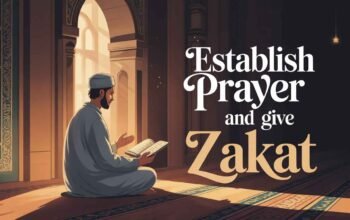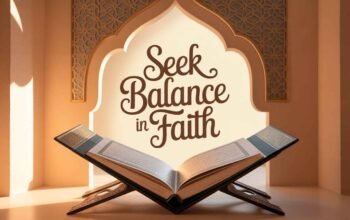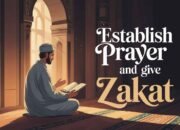Jakarta|PPMIndonesia.com– Gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk mengganti atap seng dengan genteng melalui gerakan nasional “gentengisasi” memantik perbincangan luas. Program yang menjadi bagian dari Gerakan Indonesia Asri (Aman, Sehat, Resik, Indah) itu dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama di wilayah perdesaan. Namun, di balik semangat memperindah dan menyehatkan lingkungan, muncul pertanyaan mendasar: seberapa siap struktur bangunan rumah warga untuk menanggung perubahan tersebut?
Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Sentul, Bogor, awal Februari 2026, Presiden menyoroti masih banyaknya rumah yang menggunakan atap seng. Menurutnya, seng membuat suhu rumah terasa panas dan mudah berkarat. Ia pun mendorong penggunaan genteng secara lebih luas sebagai solusi yang dinilai lebih nyaman dan estetis.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 menunjukkan, sebanyak 40.913.287 rumah tangga atau 57,93 persen telah menggunakan genteng sebagai atap rumah. Artinya, lebih dari separuh rumah tangga memang sudah memilih material tersebut. Namun, masih terdapat jutaan rumah lain yang menggunakan seng maupun material alternatif.
Dari sisi teknis, perbedaan antara seng dan genteng tidak sekadar pada tampilan. Dosen Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Ashar Saputra, mengingatkan bahwa setiap material memiliki konsekuensi struktural yang berbeda.
Seng berbentuk lembaran dan relatif ringan. Material ini dapat dipasang pada atap dengan kemiringan rendah, bahkan sekitar 5 persen, serta cenderung minim risiko kebocoran jika terpasang baik. Sebaliknya, genteng umumnya membutuhkan kemiringan lebih dari 30 persen agar dapat berfungsi optimal. Artinya, penggantian material atap tidak bisa dilakukan tanpa penyesuaian desain dan kemiringan rangka atap.
Selain itu, genteng—baik tanah liat, keramik, maupun beton—memiliki bobot lebih berat dibandingkan seng. Beban tambahan ini harus ditopang oleh struktur rangka dan dinding yang memadai. Dalam konteks Indonesia sebagai negara rawan gempa, penambahan massa bangunan tanpa perencanaan yang tepat berpotensi meningkatkan risiko kerusakan saat terjadi guncangan.
Di sisi lain, genteng memang memiliki keunggulan dalam meredam panas sehingga suhu di dalam rumah cenderung lebih sejuk. Namun, efektivitas tersebut tidak berlaku seragam di seluruh wilayah. Di daerah pegunungan yang berhawa dingin, material yang mampu menyerap dan memantulkan panas matahari justru membantu menjaga kehangatan ruangan. Dengan demikian, pilihan material atap semestinya mempertimbangkan kondisi geografis dan iklim setempat.
Aspek sosial-budaya pun tak bisa diabaikan. Indonesia memiliki keragaman arsitektur tradisional yang mencerminkan identitas lokal, mulai dari Rumah Gadang di Sumatera Barat, Tongkonan di Toraja, hingga rumah adat di Nias dan Papua. Beberapa di antaranya menggunakan ijuk atau sirap sebagai penutup atap. Penyeragaman material berpotensi menggeser karakter arsitektural yang telah lama mengakar dalam kehidupan masyarakat.
Dari sisi keberlanjutan, setiap material juga memiliki jejak energi dan emisi karbon dalam proses produksinya. Tanpa kajian menyeluruh, sulit memastikan bahwa satu jenis material selalu lebih ramah lingkungan dibandingkan yang lain. Pertimbangan ini menjadi penting dalam kebijakan pembangunan yang berorientasi jangka panjang.
Gagasan membangun Indonesia yang lebih asri tentu patut diapresiasi. Hunian yang sehat, nyaman, dan aman menjadi kebutuhan dasar warga. Namun, dalam negara dengan keragaman geografis, budaya, dan risiko bencana seperti Indonesia, kebijakan berskala nasional menuntut perencanaan yang matang dan adaptif.
Di balik atap yang hendak diganti, tersimpan persoalan struktur, keselamatan, dan konteks lokal yang tidak sederhana. Pertanyaannya kini bukan sekadar apakah genteng lebih baik dari seng, melainkan apakah setiap rumah—dan setiap wilayah—memiliki kesiapan struktural dan lingkungan untuk perubahan tersebut.