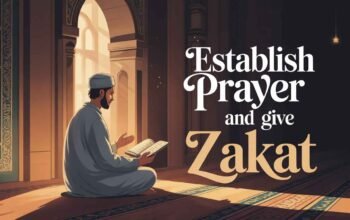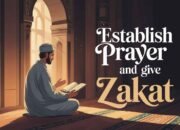Jakarta|PPMIndonesia.com- Di sebuah sudut Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, seorang anak kelas IV sekolah dasar memilih jalan yang tak pernah seharusnya menjadi pilihan anak seusianya. Usianya baru sepuluh tahun. Tangannya masih kecil. Mimpinya sederhana: belajar seperti teman-temannya.
Ia tidak meminta telepon genggam. Tidak pula sepatu mahal atau tas bermerek. Ia hanya membutuhkan buku tulis dan alat tulis—kebutuhan paling dasar bagi seorang murid sekolah dasar. Nilainya mungkin tak lebih dari sepuluh ribu rupiah. Namun bagi keluarganya, angka itu menjadi tembok yang tak terlampaui.
Beberapa hari sebelum kepergiannya, ia pulang dengan kepala tertunduk. Tugas sekolah belum dikerjakan karena tak ada buku untuk menulis. Ia menyampaikan keinginannya kepada sang ibu. Jawaban yang diterima bukan penolakan, melainkan penangguhan: “Nanti.” Kata yang lahir dari keterbatasan, bukan dari ketidakpedulian.
“Nanti” itu ternyata terlalu jauh untuk dijangkau.
Di ruang kelas, ia melihat teman-temannya menulis. Pensil bergerak, buku terbuka, pelajaran berlangsung. Ia menunduk. Rasa malu yang sunyi mengendap. Ia tidak membuat keributan. Ia tidak menangis keras. Ia hanya memikul beban yang sesungguhnya terlalu berat untuk anak sepuluh tahun.
Hingga suatu hari, bangkunya kosong. Namanya dipanggil, tak ada jawaban. Kabar yang menyusul membuat banyak orang tercekat: seorang anak mengakhiri hidupnya, didorong tekanan kemiskinan dan rasa tak berdaya menghadapi tuntutan sekolah.
Peristiwa ini bukan sekadar tragedi keluarga. Ia adalah cermin sosial. Ia memantulkan pertanyaan mendasar tentang sejauh mana negara hadir dalam kehidupan warganya yang paling rentan.
Konstitusi kita, dalam Pembukaan UUD 1945, menegaskan komitmen untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pancasila menempatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai sila penutup sekaligus tujuan. Namun di rumah sederhana di Jerebuu itu, buku tulis tak pernah sampai.
Kita memang sering berbicara tentang generasi emas, tentang Indonesia 2045, tentang bonus demografi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Anggaran pendidikan disebut sebagai yang terbesar dalam struktur APBN. Program bantuan sosial dan berbagai skema afirmasi terus diperluas.
Namun tragedi ini menunjukkan bahwa di antara angka-angka besar dan pidato optimistis, masih ada celah sunyi yang tak terjamah kebijakan. Ada keluarga yang luput dari jangkauan sistem. Ada anak yang memikul beban ekonomi orang dewasa.
Kemiskinan bukan hanya soal pendapatan yang rendah. Ia adalah akumulasi dari keterbatasan akses, rasa malu sosial, dan perasaan tertinggal. Bagi orang dewasa, kemiskinan mungkin berarti kerja tambahan, utang, atau menunda kebutuhan. Bagi anak sepuluh tahun, kemiskinan bisa berarti hilangnya rasa percaya diri—bahkan hilangnya harapan.
Lebih menyedihkan lagi, anak itu mungkin merasa dirinya menjadi beban bagi ibunya. Padahal dalam logika kemanusiaan, tak ada anak yang menjadi beban. Justru anaklah yang seharusnya dipikul bersama oleh keluarga, masyarakat, dan negara.
Tragedi ini seharusnya tidak berhenti sebagai berita duka. Ia perlu dibaca sebagai peringatan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya program. Yang lebih penting adalah sejauh mana kebijakan menyentuh rumah-rumah yang sunyi, yang tak memiliki daya tawar, dan yang sering tak terdengar suaranya.
Sekolah seharusnya menjadi ruang aman bagi anak-anak, bukan ruang yang memperbesar rasa malu karena kemiskinan. Bantuan pendidikan semestinya tak berhenti pada kebijakan di atas kertas, melainkan memastikan setiap anak benar-benar memiliki alat paling dasar untuk belajar.
Bangku kosong di kelas IV itu kini menjadi simbol. Ia mengingatkan bahwa di balik statistik kemiskinan dan indikator makroekonomi, ada wajah-wajah kecil yang menunggu perhatian nyata.
Kemerdekaan yang kita rayakan saban tahun semestinya bermakna sederhana: tak ada anak yang gagal bersekolah karena tak mampu membeli buku. Tak ada anak yang merasa hidupnya lebih ringan jika ia menghilang.
Kemiskinan memang persoalan struktural dan kompleks. Tetapi bagi seorang anak sepuluh tahun, ia hadir dalam bentuk yang sangat konkret: buku yang tak terbeli, tugas yang tak dikerjakan, dan rasa malu yang tak tertahankan.
Negara, masyarakat, dan kita semua perlu memastikan bahwa beban sebesar itu tak lagi dipikul oleh bahu sekecil itu. Karena ketika seorang anak kalah oleh kemiskinan, sesungguhnya yang kalah bukan hanya satu keluarga—melainkan nurani kebangsaan kita sendiri.