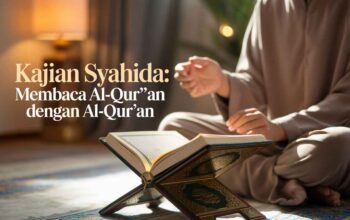ppmindonesia.com.Jakarta – Di era media sosial, batas antara pemimpin politik dan selebritas kian kabur. Para pejabat publik kini lebih sering muncul dalam bentuk potongan video: bernyanyi di panggung, berpose di warung kopi, atau membagikan momen keseharian di TikTok.
Popularitas menjadi mata uang baru dalam politik, menggantikan kredibilitas dan kapasitas.
Fenomena ini membuat politik kehilangan jiwanya sebagai ruang rasional dan etis. Ketika panggung politik berubah menjadi arena hiburan, kebijakan publik pun terancam menjadi pertunjukan semata.
Politik dalam Bayang Panggung
Perubahan besar terjadi sejak media sosial menjadi panggung utama komunikasi politik. Pemimpin tidak lagi bergantung pada media arus utama untuk membentuk citra; cukup dengan akun pribadi dan tim kreatif yang lihai mengelola narasi visual.
Video seorang pejabat menari atau membuat lelucon bisa menjangkau jutaan penonton hanya dalam hitungan jam. Tapi di balik keriuhan itu, sering kali hilang penjelasan substansial tentang visi, strategi, atau keberpihakan kebijakan.
“Politik kehilangan maknanya ketika pemimpin lebih sibuk membangun citra ketimbang membangun nalar publik.”
Fenomena ini menandai lahirnya era baru: politik performatif, di mana kekuasaan diukur bukan dari kebijakan yang dihasilkan, melainkan dari seberapa besar engagement yang diraih.
Ketika Citra Mengalahkan Kinerja
Dalam politik digital, citra dan emosi mengalahkan argumen dan data.
Sebuah unggahan dengan latar musik sentimental bisa menimbulkan simpati lebih besar dibanding laporan resmi tentang capaian pembangunan.
Politik akhirnya lebih menyerupai ajang kontes popularitas.
Pemimpin berlomba-lomba tampil menarik, bukan berpikir mendalam.
Isu-isu kompleks disederhanakan menjadi slogan, janji, dan simbol visual.
Publik pun perlahan terbiasa menilai pemimpin dari gestur dan gaya bicara, bukan dari gagasan dan integritas.
Padahal, dalam demokrasi, kepemimpinan seharusnya mengajak rakyat berpikir, bukan hanya menghibur mereka.
“Di era visual, kebenaran kalah oleh keindahan gambar. Politik pun menjadi soal pencitraan, bukan pencerahan.”
Media Sosial: Panggung Baru Kekuasaan
Media sosial, yang awalnya diharapkan membuka ruang partisipasi rakyat, justru menjadi instrumen baru pembentukan opini yang dangkal.
Algoritma lebih menyukai konten yang emosional dan mudah dikonsumsi ketimbang diskusi rasional yang panjang.
Para konsultan politik pun menyesuaikan diri. Mereka merancang strategi komunikasi berbasis trend, bukan substansi.
Kampanye politik berubah menjadi branding project, lengkap dengan narasi drama, lagu, dan simbol visual yang viral.
Akibatnya, perdebatan publik tak lagi menyinggung kebijakan, melainkan soal siapa yang paling lucu, paling hangat, atau paling “merakyat” di layar ponsel.
Pemimpin yang Tampil, Rakyat yang Terbius
Fenomena “pemimpin-selebritas” bukan hanya persoalan gaya komunikasi, tetapi juga persoalan nilai.
Ketika kekuasaan dibungkus hiburan, rakyat tak lagi diajak berpikir, melainkan hanya diminta menonton dan bersorak.
Politik yang seharusnya menjadi ruang dialektika berubah menjadi panggung pertunjukan satu arah.
Rakyat kehilangan daya kritisnya karena merasa sudah “dekat” dengan pemimpinnya di dunia maya, padahal yang mereka lihat hanyalah representasi yang dikonstruksi.
“Kedekatan semu di layar sering menggantikan akuntabilitas nyata di lapangan.”
Akibatnya, kritik dianggap kebencian, dan rasionalitas dikalahkan oleh loyalitas. Demokrasi pun pelan-pelan terjebak dalam jebakan citra.
Mendekatkan, Bukan Menipu
Bukan berarti pemimpin tidak boleh tampil hangat atau komunikatif.
Namun, kedekatan yang sejati dibangun bukan lewat video viral, melainkan lewat kehadiran nyata di lapangan, kebijakan yang berpihak, dan kesediaan untuk mendengar kritik.
Politik seharusnya menjadi seni merawat kepercayaan publik, bukan sekadar seni mempertunjukkan diri.
Pemimpin yang baik adalah ia yang mampu menjembatani jarak antara kekuasaan dan rakyatnya melalui kejujuran dan kerja nyata, bukan melalui citra digital.
Demokrasi akan tetap hidup hanya bila pemimpin dan rakyatnya sama-sama berpikir kritis, bukan saling menipu dengan ilusi kedekatan.
Menjaga Rasionalitas Demokrasi
Demokrasi digital membuka peluang besar bagi partisipasi, tetapi juga membawa risiko dangkalnya pemahaman politik.
Kita perlu membangun budaya politik baru—yang tidak menolak teknologi, tetapi menundukkannya pada etika dan akal sehat.
Ketika pemimpin kembali menempatkan substansi di atas sensasi, ketika rakyat menilai berdasarkan gagasan, bukan gaya—maka politik akan kembali ke marwahnya: alat mencapai kebaikan bersama.
“Demokrasi yang sehat hanya tumbuh di tengah rakyat yang sadar, bukan di tengah penonton yang terhibur.” (emha)