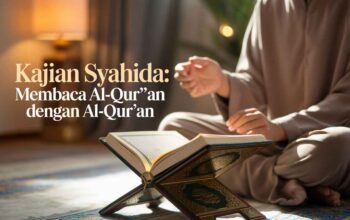ppmidonesia.com. Jakarta – Hukum dan politik kini telah berpindah panggung—dari ruang debat publik ke layar ponsel.
Apa pun yang viral segera menjadi “kebenaran” baru.
Sebuah video berdurasi tiga puluh detik bisa membentuk opini lebih kuat daripada dokumen hukum setebal seratus halaman.
Kita hidup di masa ketika like lebih berpengaruh daripada logika.
Fenomena ini menggambarkan krisis literasi hukum dan politik yang semakin dalam di tengah masyarakat digital Indonesia.
Demokrasi yang Serba Emosional
Di tengah derasnya arus media sosial, perdebatan politik dan hukum sering kali kehilangan arah.
Alih-alih berbasis argumen, ruang publik kini dipenuhi komentar emosional dan opini spontan tanpa dasar yang kuat.
Ketika Mahkamah Konstitusi membacakan putusan penting, lebih banyak warganet menonton clip reaction ketimbang membaca naskah resminya.
Begitu pula dalam politik: rakyat sibuk memperdebatkan gaya bicara pemimpin, bukan isi kebijakannya.
“Kita rajin berkomentar, tapi jarang membaca; rajin mengkritik, tapi enggan memahami.”
Demokrasi digital memang membuka kebebasan berekspresi, tapi tanpa literasi, kebebasan itu berubah menjadi kebisingan.
Antara Hukum, Hoaks, dan Histeria
Salah satu gejala paling mencolok dari krisis literasi hukum adalah mudahnya publik percaya pada kabar palsu.
Ketika sebuah kasus hukum mencuat, masyarakat cepat sekali membentuk opini tanpa memeriksa fakta.
Narasi disusun dari potongan video, bukan dari pasal undang-undang.
Opini dibangun dari tajuk yang bombastis, bukan dari isi perkara.
Padahal, hukum adalah soal ketepatan, bukan perasaan.
“Ketika emosi menggantikan argumentasi, keadilan berubah menjadi drama.”
Krisis ini bukan hanya karena rendahnya minat baca, tapi juga karena cara media sosial bekerja.
Algoritma dirancang untuk memanjakan emosi pengguna, bukan menumbuhkan nalar kritis.
Semakin marah kita, semakin sering konten itu muncul di layar.
Politik Sebagai Spektakel
Fenomena serupa terjadi dalam dunia politik.
Kampanye kini tak lagi soal gagasan, tetapi soal gaya.
Kandidat yang pandai tersenyum dan fasih bermain di media sosial sering kali lebih mudah menarik dukungan ketimbang yang tekun menjelaskan program kerja.
Politik berubah menjadi pertunjukan, dan rakyat menjadi penonton.
Pemilu diukur dari jumlah viewers, bukan dari jumlah warga yang memahami substansi kebijakan.
“Kita sedang menyaksikan politik yang lebih banyak menghibur daripada mencerdaskan.”
Masalahnya bukan hanya pada politisi, tapi juga pada publik.
Kita lebih cepat tersentuh oleh narasi personal ketimbang gagasan publik.
Kita ingin pemimpin yang “nyambung”, bukan yang berpikir.
Media Sosial dan Ilusi Partisipasi
Media sosial seolah memberi ruang bagi partisipasi rakyat.
Namun sering kali, partisipasi itu hanya sebatas klik, komentar, dan share.
Kita merasa sudah ikut berpolitik hanya karena menulis status atau memberi emoji marah di kolom komentar.
Padahal, partisipasi sejati memerlukan keterlibatan rasional—memahami isu, menimbang argumen, dan menuntut akuntabilitas.
Tanpa itu, politik digital hanyalah pesta pikiran yang dangkal.
“Kita mengira sedang berpartisipasi, padahal hanya sedang terhibur oleh kegaduhan.”
Membangun Literasi, Menjaga Akal Sehat
Krisis literasi hukum dan politik tidak bisa diatasi dengan imbauan moral semata.
Ia butuh strategi nasional yang melibatkan pendidikan, media, dan masyarakat sipil.
Pertama, pendidikan kewargaan digital harus diajarkan sejak dini.
Siswa perlu dilatih untuk berpikir kritis terhadap informasi hukum dan politik yang mereka temui di dunia maya.
Kedua, media arus utama perlu kembali menegaskan fungsinya sebagai penjernih, bukan sekadar penyalur informasi.
Kecepatan boleh penting, tetapi kedalaman jauh lebih bermakna.
Ketiga, pemimpin publik perlu menjadi teladan dengan komunikasi yang jujur dan edukatif, bukan sekadar viral.
“Rakyat tidak butuh pemimpin yang pandai bermain algoritma, tapi yang mampu menuntun logika.”
Menutup dengan Kesadaran Baru
Kita mungkin tak bisa menolak era digital, tapi kita bisa memilih cara hidup di dalamnya.
Di antara banjir informasi, tugas kita adalah menjaga kejernihan berpikir.
Sebab, demokrasi yang sehat hanya bisa tumbuh di atas fondasi rasionalitas, bukan popularitas.
Kita boleh berdebat di dunia maya, tapi marilah kita belajar kembali membaca dengan hati dan berpikir dengan nalar.
Karena hanya dengan begitu, like tidak lagi mengalahkan logika. (acank)