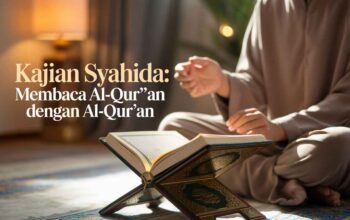Jakarta.PPMIndonesia.com- Belakangan ini, dunia menyaksikan bagaimana Amerika Serikat—yang kerap mengklaim diri sebagai kampiun demokrasi—dituding melancarkan serangan militer ke Caracas, Venezuela. Dalam laporan tersebut, Presiden Nicolás Maduro dan istrinya disebut ditangkap, bahkan simbol perjuangan nasional Venezuela, Mausoleum Hugo Chávez, turut menjadi sasaran.
Peristiwa ini menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya dipraktikkan sebagai sistem politik, tetapi juga dijadikan alat perang persepsi. Atas nama demokrasi, kedaulatan sebuah bangsa dapat dilanggar.
Perang persepsi inilah yang kini merembes ke Indonesia. Demokrasi liberal ala Barat, khususnya konsep pemilihan langsung, terus digulirkan dan dipromosikan seolah sebagai satu-satunya bentuk demokrasi yang sah. Padahal, sistem ini bertentangan secara fundamental dengan Demokrasi Pancasila yang berlandaskan permusyawaratan perwakilan.
Indonesia hari ini tengah digerogoti oleh perang persepsi: semua orang bicara seakan paling benar, tanpa berpijak pada perjanjian luhur bangsa yang telah dirumuskan para pendiri negara. Puncaknya adalah amandemen UUD 1945 yang faktanya bukan sekadar perubahan pasal, melainkan penggantian sistem ketatanegaraan secara menyeluruh.
Amandemen yang Meruntuhkan Bangunan Keindonesiaan
Penggantian UUD 1945 menjadi UUD 2002 telah mengubah secara radikal bangunan negara. Bukan hanya MPR yang dilemahkan, tetapi aliran pemikiran keindonesiaan ikut diruntuhkan.
Visi dan misi negara yang bersifat kolektif diganti dengan puluhan visi-misi individual: Presiden, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Akibatnya, tujuan negara—keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia—kehilangan arah dan makna.
Sistem ketatanegaraan pun bergeser dari kolektivisme perwakilan menuju presidensialisme liberal berbasis individualisme. Demokrasi permusyawaratan digantikan oleh demokrasi mayoritas—banyak-banyakan suara—yang menjadikan politik sebagai arena pertarungan kalah-menang, kuat-kuatan modal, dan kaya-kayaan.
Pemilihan langsung yang mahal melahirkan ketergantungan pada bandar dan rentenir politik. Presiden, kepala daerah, hingga anggota legislatif membutuhkan investor politik. Maka lahirlah demokrasi biaya tinggi yang sarat pencitraan, kebohongan kampanye, dan politik post-truth.
Rakyat pun ditipu. Demokrasi direduksi menjadi sekadar one man one vote, padahal prinsip itu justru bertentangan dengan Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm, sumber dari segala sumber hukum.
Oligarki dan Perampasan Kedaulatan Rakyat
Biaya politik yang tinggi melahirkan praktik suap-menyuap yang dianggap wajar. Di akar rumput muncul istilah sinis: NPWP—Nomor Piro Wani Piro. Politik menjadi sangat pragmatis.
Ketika kekuasaan diraih, tidak ada makan siang gratis. Para oligark menagih balas jasa. Tidak mengherankan jika 0,2% elite menguasai sekitar 70% lahan di republik ini, sementara regulasi dipermudah demi kepentingan mereka.
Kasus PIK II, Morowali, Halmahera, dan Maluku memperlihatkan bagaimana kekayaan alam digaruk, pajak diringankan, tenaga kerja asing didatangkan, sementara rakyat justru dimiskinkan oleh beban pajak.
Penyimpangan Fundamental Ketatanegaraan
Penggantian UUD 1945 telah melahirkan sejumlah penyimpangan mendasar:
- UUD 1945 diganti UUD 2002, bukan diamandemen secara terbatas.
- Visi-misi negara diganti visi-misi individual, menghapus arah kolektif bangsa.
- Kedaulatan rakyat direbut partai politik, lalu diklaim “dijalankan oleh UUD”.
- MPR didegradasi menjadi lembaga tinggi biasa tanpa kewenangan strategis.
- Demokrasi permusyawaratan diganti demokrasi mayoritas suara.
- GBHN dihapus, padahal ia adalah penjabaran visi negara.
- Ideologi Pancasila direduksi, digantikan praktik liberalisme, individualisme, dan kapitalisme.
- Presiden tidak lagi disyaratkan orang Indonesia asli, melainkan sekadar warga negara.
- Keunikan negara kebangsaan Indonesia dihapus, digantikan logika negara demokrasi liberal.
Indonesia bukan negara demokrasi liberal. Indonesia adalah negara kebangsaan yang keputusan politiknya ditempuh melalui permusyawaratan perwakilan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, bukan oleh suara terbanyak.
Kedaulatan Rakyat yang Dikosongkan
Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen menyatakan:
“Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.”
Setelah amandemen, berubah menjadi:
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”
Formulasi ini kabur. Pelaksanaan kedaulatan tidak lagi jelas subjek dan mekanismenya. Ditambah penghapusan utusan golongan dan utusan daerah, kedaulatan rakyat sejatinya telah dirampas oleh elite partai politik.
Ironisnya, mereka yang mengampanyekan pemilihan langsung mengklaim memperjuangkan kedaulatan rakyat, tetapi menolak mengembalikan mekanisme representasi sejati. Di balik itu, tersimpan agenda tersembunyi oligarki.
Demokrasi untuk Rakyat atau Rakyat untuk Demokrasi?
Pemilu 2019 menelan ratusan korban petugas KPPS. Biaya pemilu 2024 diperkirakan mencapai Rp110 triliun. Pertanyaannya: apakah sistem ini benar-benar menjaga persatuan dan keadilan?
Demokrasi seharusnya menjadi alat untuk kesejahteraan rakyat, bukan sebaliknya. Bung Karno telah lama mengingatkan tentang bahaya kompromi dengan liberalisme dan neokolonialisme, yang menggerogoti jiwa revolusi dan menjauhkan bangsa dari UUD 1945 dan Pancasila.
Kesimpulan
Bangsa ini harus berani jujur mengakui bahwa arah negara telah melenceng dari Pembukaan UUD 1945, Pancasila, dan cita-cita keadilan sosial.
Titik pijak untuk meluruskan kembali perjalanan bangsa adalah kembali kepada UUD 1945 yang asli dan Demokrasi Pancasila, bukan demokrasi liberal yang bertumpu pada uang dan manipulasi persepsi.
Jika perjuangan ini dilakukan dengan keikhlasan demi bangsa dan negara, niscaya rahmat dan pertolongan Allah akan menyertai, untuk mengembalikan Indonesia pada tujuan hakikinya:
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Merdeka! ✊
Oleh: Prihandoyo Kuswanto
Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila & Dewan Pengawas Koperasi Peranserta Masyarakat (KOPERMAS) Nusantara