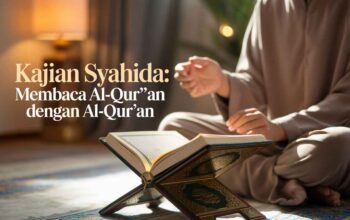Jakarta|PPMIndonesia.com- Relasi suami-istri dalam Islam kerap dibaca melalui kacamata kekuasaan: siapa memimpin, siapa tunduk, siapa berhak memerintah, dan siapa wajib menaati. Cara baca seperti ini tidak lahir dari ruang hampa. Ia berakar pada budaya patriarkal yang sudah mapan jauh sebelum Al-Qur’an diturunkan, lalu diwariskan dari generasi ke generasi sebagai “ajaran agama”.
Masalahnya, ketika tafsir yang sarat kepentingan itu dianggap suci, Al-Qur’an tidak lagi dibaca sebagai petunjuk, melainkan sebagai pembenaran. Ayat-ayat dipilih, dipotong, bahkan dimaknai secara sepihak untuk mengokohkan relasi kuasa. Dalam konteks inilah pendekatan kajian syahida—membiarkan Al-Qur’an menjadi saksi atas dirinya sendiri—menjadi penting.
Tulisan ini berupaya membaca ulang relasi suami-istri dengan metode Qur’an bil Qur’an, agar relasi tersebut kembali diletakkan dalam horizon tauhid, bukan dominasi.
Agama Kekuasaan dan Kritik Al-Qur’an
Al-Qur’an sejak awal datang untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia. Karena itu, kitab suci ini sangat kritis terhadap keberagamaan yang hanya mengikuti warisan tanpa kesadaran:
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا۟ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا۟ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ
“Apabila dikatakan kepada mereka, ‘Ikutilah apa yang telah Allah turunkan,’ mereka menjawab, ‘Tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami.’”
(QS al-Baqarah [2]: 170)
Dalam relasi suami-istri, pola “agama warisan” ini tampak jelas ketika tafsir yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang harus tunduk diterima begitu saja, tanpa diuji ulang oleh keseluruhan kesaksian Al-Qur’an.
QS an-Nisā’ (4): 34 dan Titik Bias Kekuasaan
Ayat yang paling sering dijadikan dasar relasi kuasa adalah QS an-Nisā’ ayat 34:
ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍۢ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ
“Kaum laki-laki adalah penanggung jawab bagi perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka menafkahkan sebagian dari harta mereka. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah perempuan-perempuan yang taat (qaanitaat), yang menjaga apa yang Allah jaga ketika tidak terlihat.”
(QS an-Nisā’ [4]: 34)
Bias kekuasaan muncul ketika kata qaanitaat diterjemahkan sebagai “taat kepada suami”, padahal Al-Qur’an sendiri tidak pernah menggunakan istilah itu untuk ketaatan kepada manusia.
Qaanitaat: Kesaksian Al-Qur’an tentang Ketaatan
Al-Qur’an menjadi saksi yang konsisten bahwa qanata dan turunannya selalu bermakna ketaatan kepada Allah.
Tentang Maryam, Allah berfirman:
وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَٰنِتِينَ
“Dan ia (Maryam) termasuk orang-orang yang taat.”
(QS at-Tahrīm [66]: 12)
Maryam tidak memiliki suami. Maka ketaatan yang dimaksud tidak mungkin diarahkan kepada manusia, melainkan kepada Allah semata.
Kesaksian ini ditegaskan kembali dalam ayat lain:
إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَٰتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْقَٰنِتِينَ وَٱلْقَٰنِتَٰتِ
“Sungguh, laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang beriman, laki-laki dan perempuan yang taat…”
(QS al-Ahzāb [33]: 35)
Al-Qur’an, melalui kesaksiannya sendiri, menolak pembacaan yang memindahkan ketaatan vertikal kepada Allah menjadi ketaatan horizontal kepada suami.
“Fa-in Atha’nakum”: Ketaatan atau Kesadaran?
Bagian lanjutan QS 4:34 berbunyi:
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا
“Kemudian jika mereka menuruti kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka.”
Sering kali ayat ini diterjemahkan sebagai “jika mereka kembali taat”, padahal kata “kembali” tidak ada dalam teks Arab. Penambahan ini bukan netral, melainkan ideologis.
Secara tekstual:
- Huruf fa (ف) menghubungkan frasa ini dengan langkah sebelumnya: nasihat, jeda emosional, dan pemisahan ranjang.
- Maka atha‘nakum menunjuk pada respons istri terhadap upaya rekonsiliasi, bukan kepatuhan struktural dalam pernikahan.
Ayat berikutnya bahkan menegaskan bahwa konflik rumah tangga diselesaikan melalui mediasi dua keluarga (QS 4:35), bukan melalui otoritas sepihak suami.
Nushooz dan Kesetaraan Moral
Istilah نُشُوز (nushooz) juga sering dipersempit maknanya menjadi “pembangkangan istri”. Padahal Al-Qur’an menggunakan istilah yang sama untuk suami:
وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنۢ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا
“Jika seorang perempuan khawatir akan nushooz atau sikap berpaling dari suaminya…”
(QS an-Nisā’ [4]: 128)
Ini menjadi kesaksian penting bahwa nushooz bukan soal siapa taat kepada siapa, melainkan soal retaknya komitmen moral dan emosional dalam pernikahan.
Pernikahan dalam Horizon Tauhid
Al-Qur’an menempatkan pernikahan dalam bingkai ketenteraman, kasih, dan rahmat:
وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً
“Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan pasangan hidup dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang.”
(QS ar-Rūm [30]: 21)
Relasi suami-istri bukan relasi penguasa dan yang dikuasai, melainkan dua hamba Allah yang setara secara moral, saling menopang dalam ketaatan kepada-Nya.
Penutup: Al-Qur’an sebagai Saksi, Bukan Alat Kuasa
Ketika Al-Qur’an dibiarkan menjadi saksi atas dirinya sendiri, menjadi jelas bahwa:
- Al-Qur’an tidak membenarkan relasi suami-istri yang berbasis dominasi.
- Ketaatan dalam Islam bersifat vertikal kepada Allah, bukan horizontal sebagai alat kontrol.
- Bias kekuasaan lahir bukan dari wahyu, melainkan dari tafsir yang diwariskan tanpa diuji.
Membaca Al-Qur’an tanpa bias kekuasaan bukan berarti meniadakan peran dan tanggung jawab, melainkan mengembalikannya ke tempat yang benar: di bawah tauhid, keadilan, dan kasih sayang.