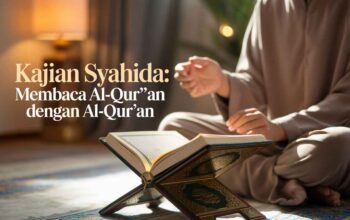ppmindonesia.com.Jakarta– Demokrasi seharusnya tumbuh dari nalar publik yang sehat, bukan dari sorak-sorai massa yang terpesona. Namun, politik Indonesia kini sering tampak lebih mirip panggung hiburan daripada forum kebijakan.
Pemimpin diperlakukan seperti selebritas, rakyat menjadi penonton, dan kritik berubah menjadi ancaman. Inilah wajah baru demokrasi kita: demokrasi yang bergeser dari rasionalitas menuju ritual pemujaan.
Politik di Era Citra
Kehidupan politik modern dikuasai oleh citra. Figur politik bukan lagi dinilai dari gagasan dan rekam jejak, tetapi dari cara ia tampil di layar kaca dan media sosial.
Kampanye menjadi pertunjukan visual, dan kebenaran sering kalah oleh viralitas. “Kita sedang hidup di masa ketika yang dikagumi bukan isi pikirannya, tapi gaya bicaranya,”
“Ketika politik berubah menjadi panggung pemujaan, rakyat berhenti menjadi warga dan menjadi penonton.” ujar Guru Gembul**
Demokrasi yang Kehilangan Daya Kritis
Krisis demokrasi hari ini bukan karena kurangnya partisipasi rakyat, tetapi karena hilangnya kualitas partisipasi. Masyarakat hadir di ruang politik, tetapi tidak membawa pertanyaan kritis.
Kita bersemangat mendukung, namun enggan menilai dengan jernih. Kultus terhadap figur politik mematikan tradisi berpikir.
Pemimpin yang seharusnya diawasi justru dipuja; yang mestinya dikritik malah dilindungi dari pertanyaan. Ruang publik yang seharusnya menjadi tempat perdebatan ide berubah menjadi arena fanatisme.
Di titik ini, demokrasi kehilangan fungsi pendidikannya. Ia tidak lagi melatih warga menjadi rasional, tetapi hanya memelihara loyalitas emosional.
Media Sosial dan Ekonomi Emosi
Peran media sosial semakin memperkuat budaya pemujaan. Setiap pernyataan politik langsung menjadi konten.
Kemarahan, kesetiaan, dan cinta buta diperdagangkan dalam bentuk engagement. Politik pun kehilangan nilai deliberatifnya—tak lagi membicarakan kebijakan, tapi siapa yang paling disukai.
Fenomena ini menciptakan apa yang disebut para sosiolog sebagai emotional democracy—demokrasi yang digerakkan oleh emosi, bukan logika.Dan begitu emosi mengambil alih, rasionalitas publik terpinggirkan.
Jalan Pulang: Mengembalikan Akal Sehat Politik
Demokrasi sejati hanya bisa hidup bila warga mau berpikir. Kritik bukan tanda permusuhan, tetapi ekspresi cinta pada kebenaran.
Kita harus berani menilai pemimpin dengan akal, bukan dengan perasaan. Pemimpin yang baik bukan yang disembah, melainkan yang mau dipertanggungjawabkan.
Guru Gembul mengingatkan, “Kalau rakyat berhenti berpikir, maka pemimpin akan berhenti mendengar.**”
Pesan ini sederhana tapi penting: hanya dengan akal sehat, demokrasi bisa diselamatkan dari jebakan pemujaan figur.
“Demokrasi bukan panggung penyembahan, tapi ruang percakapan antara pikiran dan nurani.* (acank)