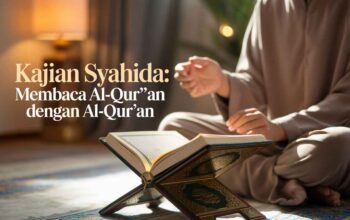ppmindonesia.com.Jakarta – Konflik internal di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memasuki fase krusial. Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan bahwa dirinya masih menjabat sebagai Ketua Umum PBNU yang sah secara hukum dan konstitusi organisasi. Penegasan itu disampaikan melalui pernyataan sikap resmi yang ditandatangani langsung oleh Gus Yahya pada 13 Desember 2025.
Pernyataan tersebut muncul sebagai respons atas keputusan Rapat Pleno PBNU pada 9–10 Desember 2025 di Hotel Sultan, Jakarta, yang menyatakan pemberhentian Gus Yahya dan menetapkan KH Zulfa Mustofa—sebelumnya Wakil Ketua Umum PBNU—sebagai Pejabat Sementara (PJS) Ketua Umum PBNU hingga Muktamar 2026.
Pleno itu disebut sebagai tindak lanjut dari Risalah Rais Aam PBNU tertanggal 20 November 2025 yang digelar di Hotel Aston, Jakarta. Namun, alih-alih meredakan ketegangan, keputusan tersebut justru memantik perdebatan luas di kalangan Nahdliyin.
Bukan Sekadar Figur, Tapi Tafsir Konstitusi
Perdebatan yang muncul tidak semata menyangkut sosok pimpinan, melainkan menyentuh isu yang lebih mendasar: bagaimana PBNU membaca konstitusi organisasi, menafsirkan keadaan darurat, serta memaknai adab sebagai fondasi etik kepemimpinan ulama.
Pihak yang mendukung penetapan PJS berargumen bahwa langkah tersebut diperlukan demi menjaga kesinambungan organisasi. Rujukan yang kerap dikemukakan adalah pandangan Wakil Ketua Rais Aam PBNU KH Afifuddin Muhajir, yang menilai bahwa dalam kondisi darurat, penyimpangan prosedural dapat dibenarkan.
Pandangan ini berpijak pada kaidah ushul fiqh adh-dharurat tubihul mahzurat—bahwa kondisi darurat dapat membolehkan hal-hal yang semula terlarang. Namun dalam tradisi fikih, kaidah darurat tidak pernah berdiri sendiri. Ia dibatasi oleh prinsip adh-dharuratu tuqaddaru bi qadariha—bahwa darurat harus diukur sebatas kebutuhannya.
Pertanyaan kuncinya kemudian mengemuka: apakah penetapan PJS benar-benar membatasi mudarat, atau justru memperluasnya?
Legitimasi Setara, Kewenangan Dipersoalkan
Di sisi lain, penolakan terhadap keputusan pleno PBNU berpijak pada argumen konstitusional yang tak kalah kuat. Rais Aam dan Ketua Umum PBNU sama-sama dipilih melalui forum tertinggi organisasi, Muktamar, sehingga memiliki legitimasi setara. Dalam kerangka ini, perubahan kepemimpinan dinilai tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh salah satu unsur.
Karena itu, risalah dan seluruh produk turunannya—termasuk penetapan PJS Ketua Umum PBNU—dipandang melampaui kewenangan konstitusional organisasi.
Antara Konstitusi dan Adab
Perdebatan semakin kompleks dengan hadirnya pandangan Nadirsyah Hosen, akademisi hukum Islam dan mantan Ketua PCINU Australia. Ia mengingatkan bahwa NU bukan sekadar organisasi hukum, melainkan sebuah peradaban adab. Ketaatan tekstual pada AD/ART tanpa kebijaksanaan, menurutnya, berisiko mengeringkan ruh keulamaan.
Namun, diskursus yang berkembang belakangan justru terjebak pada dikotomi yang keliru: memilih antara konstitusi atau adab. Dalam tradisi NU, keduanya tidak pernah dipertentangkan. Konstitusi lahir dari adab, dan adab menemukan bentuk operasionalnya melalui konstitusi.
Kaidah ushul fiqh al-umuru bi maqasidiha—setiap perkara dinilai dari tujuan akhirnya—menjadi jembatan penting. Tujuan kepemimpinan PBNU bukan sekadar menjaga struktur organisasi, melainkan menjaga keteduhan umat dan kewibawaan ulama.
Polarisasi dan Wacana Muktamar Luar Biasa
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penetapan PJS belum sepenuhnya meredakan ketegangan. Polarisasi justru menguat. Seruan pengendalian diri dari para sesepuh NU di Ploso dan Tebuireng agar semua pihak menahan diri belum sepenuhnya direspons.
Wacana penyelenggaraan Muktamar Luar Biasa (MLB), sebagaimana disampaikan Wakil Presiden RI ke-13 KH Ma’ruf Amin, mengemuka sebagai salah satu opsi penjernihan. Hal ini menandakan bahwa potensi kerusakan yang dikhawatirkan belum sepenuhnya terhindarkan.
Belajar dari Preseden Cipete–Situbondo
NU sejatinya memiliki preseden sejarah yang relevan. Pada akhir 1970-an hingga awal 1980-an, NU pernah berada dalam ketegangan serius antara poros Cipete—yang merujuk pada kepemimpinan KH Idham Chalid—dan Situbondo, yang merepresentasikan kegelisahan ulama pesantren untuk mengembalikan NU ke Khittah 1926.
Dalam situasi genting itu, peran tiga ulama kunci menjadi penentu: KH Achmad Siddiq, KH Ali Maksum, dan KH As’ad Syamsul Arifin. Konflik tidak diselesaikan dengan saling menyingkirkan, melainkan dikembalikan ke mekanisme tertinggi organisasi melalui Muktamar NU ke-27 di Situbondo tahun 1984—sebuah rekonsiliasi besar yang menyelamatkan NU dari perpecahan.
Ujian Kebesaran Jiwa Ulama
Konflik PBNU hari ini memberi pelajaran penting: konstitusi memang perlu, tetapi tidak pernah cukup sendirian. AD/ART adalah pagar agar organisasi tidak liar, tetapi adab dan kebijaksanaan adalah jiwa yang membuat NU tetap hidup dan bermartabat.
Fenomena yang terjadi juga menandai pergeseran locus of authority—dari tatanan konstitusional menuju kontestasi legitimasi berbasis klaim moral, simbolik, dan kekuasaan. Jika dibiarkan tanpa koreksi, marwah kepemimpinan ulama berisiko tereduksi menjadi perebutan kekuasaan biasa.
Padahal, PBNU adalah poros moderasi Islam Indonesia dan rumah spiritual bagi lebih dari 100 juta warga Nahdliyin. Ketika NU tidak teduh, psikologi keagamaan bangsa ikut terguncang.
Pada akhirnya, ujian terbesar kepemimpinan PBNU hari ini bukan semata soal sah atau tidak sah secara formal, melainkan soal kebesaran jiwa. Apakah para pemangku mandat bersedia mengalah demi islah? Apakah mereka sanggup menahan langkah yang mungkin sah secara prosedural, tetapi berisiko melukai ketenangan umat?
Sejarah NU menunjukkan bahwa organisasi ini bertahan bukan karena kemenangan tafsir hukum, melainkan karena kebijaksanaan ulama yang memilih maslahat di atas ambisi. Di sanalah adab memandu konstitusi, dan kebijaksanaan mengarahkan keputusan.