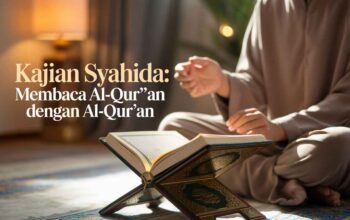ppmindonesia.com.Jakarta — Kontroversi seputar sawit dan deforestasi kembali mengemuka setelah pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta publik agar tidak takut terhadap deforestasi. Pernyataan tersebut memicu reaksi dari berbagai kalangan, mulai dari mantan pejabat publik hingga akademisi, yang menilai bahwa pendekatan tersebut berpotensi menyederhanakan persoalan hutan dan mengabaikan dampak ekologis serta sosial yang luas.
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) termasuk yang secara terbuka menyuarakan kritik. Ia mengingatkan bahwa perluasan sawit tidak bisa dilepaskan dari persoalan keadilan agraria dan tata kelola sumber daya alam. Pengalamannya saat menjabat Bupati Belitung Timur menjadi rujukan utama dalam pandangannya.
Ahok menyoroti praktik kemitraan plasma sawit yang selama ini diklaim berpihak pada rakyat. Menurutnya, di lapangan skema 20 persen–80 persen kerap hanya bersifat administratif. “Banyak ditemukan praktik nomine, pinjam nama orang. Secara aturan terlihat patuh, tetapi substansinya rakyat tidak memiliki,” ujarnya.
Karena itu, Ahok mengusulkan agar lahan perkebunan—terutama lahan yang disita negara—tidak dialihkan kepada korporasi besar atau BUMN, melainkan menjadi aset desa yang dikelola melalui koperasi rakyat. Dalam skema tersebut, pengusaha tetap mengelola kebun, warga desa bekerja dan menerima upah, sementara keuntungan dikembalikan ke desa.
“Harusnya yang memegang lahan itu koperasi rakyat, bukan BUMN,” tegasnya.
Ahok juga menyatakan penolakannya terhadap perluasan sawit di Papua, termasuk jika alasan yang dikemukakan adalah swasembada energi. Menurutnya, Papua memiliki hutan dengan nilai ekologis dan sosial yang tidak dapat digantikan oleh perkebunan monokultur.
Kritik lebih konseptual disampaikan akademisi kehutanan. pakar sosiologi dan ekologi politik terkemuka dari IPB University, Arya Hadi Dharmawan, dalam sebuah surat terbuka kepada Presiden Prabowo, menyampaikan keprihatinannya atas pernyataan yang menyamakan sawit dengan tanaman hutan hanya karena sama-sama berdaun hijau dan menyerap karbon.
“Hutan tidak melulu soal karbon. Ia adalah sistem kehidupan yang kompleks, yang mencakup keanekaragaman hayati, tata air, iklim lokal, hingga ruang hidup masyarakat adat,” tulis Arya.
Menurutnya, hutan menyediakan fungsi ekologis dan sosial yang tidak dapat digantikan oleh perkebunan sawit. Hutan menjadi habitat satwa liar, sumber tanaman obat, penjaga keseimbangan hidrologi, serta penyangga kehidupan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.
Sebaliknya, perkebunan sawit dinilai sebagai ekosistem monokultur yang miskin keanekaragaman hayati dan sangat bergantung pada logika pasar. “Secara fisik daun memang hijau, tetapi menyamakan ekosistem sawit dengan hutan bukanlah perbandingan yang setara,” tegasnya.
Dalam surat terbukanya, Arya juga mengingatkan bahwa meskipun sawit memberikan kontribusi ekonomi besar, kehidupan bangsa tidak bisa disederhanakan hanya dalam ukuran rupiah. Nilai ekologis hutan—air, oksigen, keanekaragaman hayati, dan pengetahuan herbal—tidak mungkin dihitung secara ekonomi, tetapi manfaatnya dirasakan lintas generasi.
Ia mengajak Presiden dan jajaran menteri untuk membuka ruang dialog yang lebih luas dengan para ahli kehutanan, ekologi, sosiologi, dan antropologi sebelum mengambil kebijakan strategis terkait sawit dan hutan. Menurutnya, pengembangan sawit untuk pangan dan energi masih dapat dilakukan tanpa harus membuka kawasan hutan baru.
“Presiden seharusnya berada di garis terdepan dalam menolak deforestasi dengan segala dampak negatifnya, bukan menormalkannya,” tulis Arya.
Kontroversi ini menegaskan bahwa isu sawit dan deforestasi bukan sekadar perdebatan teknis, melainkan soal pilihan moral dan arah pembangunan nasional. Di tengah krisis iklim dan meningkatnya bencana ekologis, negara dituntut hadir tidak hanya sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga sebagai penjaga kehidupan dan keberlanjutan.
Surat terbuka tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan yang mengorbankan hutan berisiko mewariskan krisis ekologis dan sosial bagi generasi mendatang. Di sinilah kebijakan sawit diuji: apakah akan terus berpihak pada ekspansi modal, atau bertransformasi menuju pembangunan yang adil dan berkelanjutan.(acank)