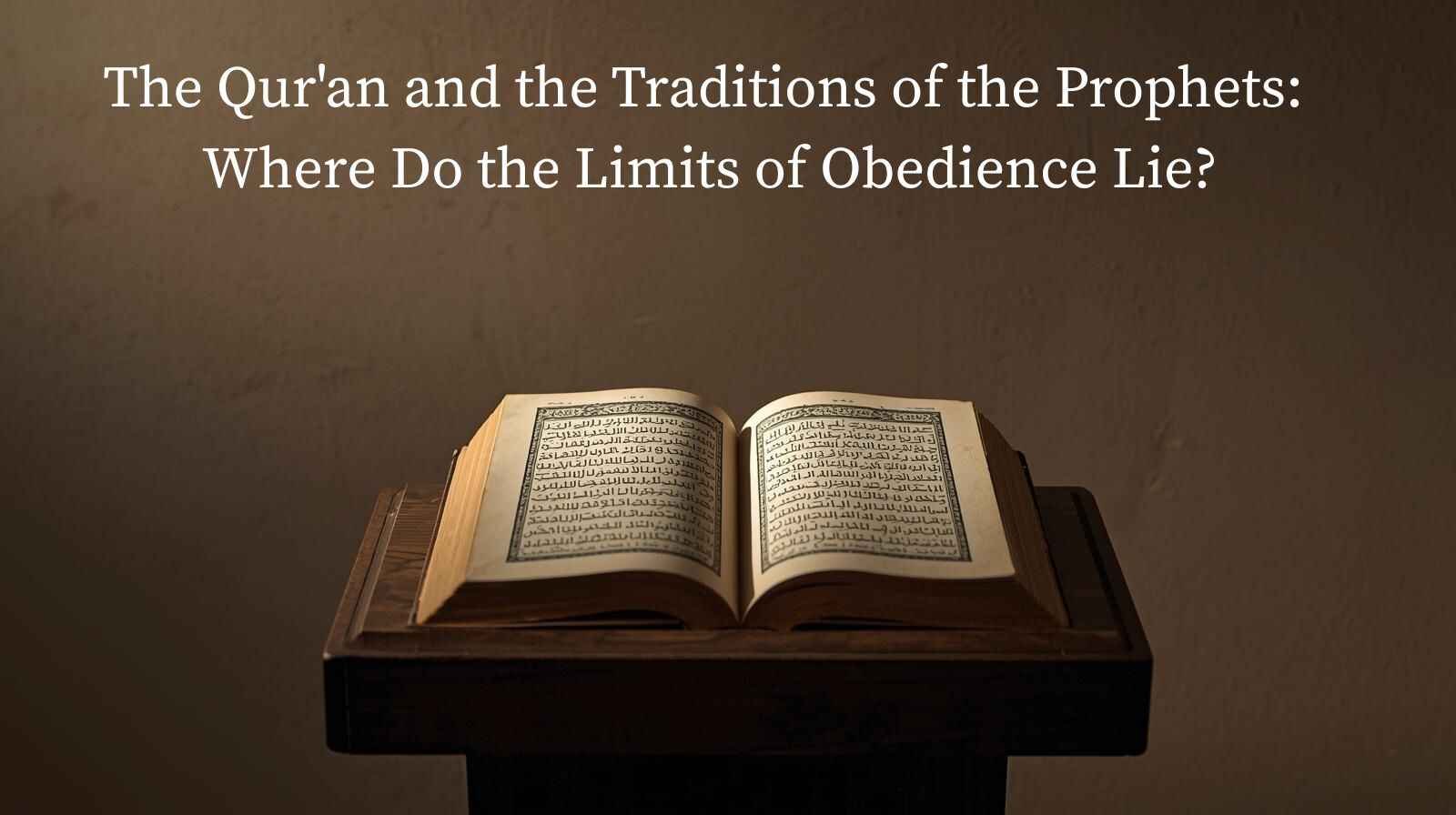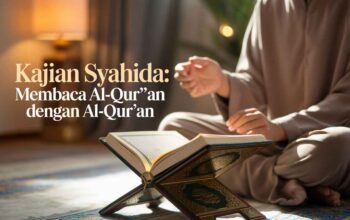Jakarta,PPMINdonesia.com- Dalam perjalanan sejarah Islam, umat tidak hanya berinteraksi dengan Al-Qur’an sebagai wahyu utama, tetapi juga dengan tradisi riwayat yang berkembang setelahnya. Hadits, atsar, dan berbagai bentuk penjelasan keagamaan menjadi bagian penting dalam praktik keberagamaan umat Islam. Namun, pertanyaan mendasar yang terus relevan untuk diajukan adalah: di mana letak batas ketaatan antara wahyu Ilahi dan riwayat manusia?
Melalui pendekatan Qur’an bil Qur’an, Al-Qur’an tidak hanya menyampaikan ajaran, tetapi juga memberikan kerangka etik dan epistemologis tentang bagaimana sumber-sumber selain wahyu harus diposisikan. Al-Qur’an berbicara tentang dirinya sendiri, tentang otoritasnya, serta tentang sikap kritis dan bertanggung jawab dalam mengikuti sesuatu atas nama agama.
Al-Qur’an sebagai Otoritas Tertinggi
Al-Qur’an secara eksplisit menegaskan posisinya sebagai rujukan utama dan final dalam urusan petunjuk hidup. Allah berfirman:
ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ
“Kitab (Al-Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 2)
Ayat ini tidak hanya menegaskan kebenaran Al-Qur’an, tetapi juga menempatkannya sebagai standar hidayah. Dalam pendekatan Qur’an bil Qur’an, ayat ini dipahami selaras dengan penegasan lain:
وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ
“Telah sempurna kalimat Tuhanmu sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat-Nya.”
(QS. Al-An‘am [6]: 115)
Kesempurnaan wahyu inilah yang menjadi fondasi utama dalam menimbang segala bentuk penjelasan, tradisi, dan riwayat yang muncul kemudian.
Makna Hadits dalam Al-Qur’an
Menarik untuk dicermati bahwa Al-Qur’an sendiri menggunakan istilah hadīts, tetapi dalam makna yang lebih luas sebagai perkataan, cerita, atau narasi. Salah satu ayat kunci menyatakan:
اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ
“Allah telah menurunkan perkataan (hadits) yang paling baik, yaitu Kitab (Al-Qur’an) yang serasi lagi berulang-ulang.”
(QS. Az-Zumar [39]: 23)
Dalam perspektif Qur’an bil Qur’an, ayat ini beresonansi dengan pertanyaan retoris Allah:
فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ
“Maka kepada perkataan (hadits) apa lagi setelah Al-Qur’an itu mereka akan beriman?”
(QS. Al-Mursalat [77]: 50)
Rangkaian ayat ini tidak sedang menolak keberadaan riwayat, tetapi menegaskan prioritas iman dan ketaatan. Al-Qur’an memosisikan dirinya sebagai ahsan al-hadīts—narasi terbaik dan paling otoritatif.
Ketaatan kepada Rasul dalam Bingkai Wahyu
Salah satu perdebatan yang sering muncul adalah hubungan antara ketaatan kepada Rasul dan tradisi riwayat. Al-Qur’an secara tegas memerintahkan ketaatan kepada Rasul, namun dalam kerangka yang sangat jelas:
مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ
“Barang siapa menaati Rasul, maka sungguh ia telah menaati Allah.”
(QS. An-Nisa’ [4]: 80)
Namun Al-Qur’an juga menegaskan fungsi Rasul sebagai penyampai wahyu, bukan pembuat ajaran independen:
وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ
“Dan ia (Muhammad) tidak berbicara menurut hawa nafsunya. Ucapannya tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan.”
(QS. An-Najm [53]: 3–4)
Dalam kajian Qur’an bil Qur’an, ayat-ayat ini dipahami sebagai penegasan bahwa ketaatan kepada Rasul bersifat integral dengan ketaatan kepada wahyu, bukan ketaatan buta kepada semua bentuk narasi yang dinisbatkan secara historis.
Peringatan terhadap Otoritas Selain Wahyu
Al-Qur’an juga memberi peringatan keras tentang bahaya mengikuti otoritas selain Allah tanpa dasar yang jelas:
اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ
“Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah.”
(QS. At-Taubah [9]: 31)
Ayat ini, jika dikaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya, mengajak umat Islam untuk waspada terhadap sakralisasi manusia, termasuk dalam bentuk otoritas keagamaan yang tidak diuji kembali dengan Al-Qur’an.
Di Mana Letak Batas Ketaatan?
Dari keseluruhan ayat tersebut, Al-Qur’an tampaknya mengarahkan umat pada satu prinsip kunci:
ketaatan mutlak hanya milik Allah dan wahyu-Nya, sementara selain itu berada dalam wilayah ijtihad, penalaran, dan tanggung jawab moral.
وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ
“Dan bahwa inilah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah ia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan lain.”
(QS. Al-An‘am [6]: 153)
Dalam kerangka ini, tradisi riwayat tidak serta-merta ditolak, tetapi ditimbang, diuji, dan diposisikan agar tidak melampaui batas ketaatan yang seharusnya hanya diberikan kepada wahyu.
Penutup
Pendekatan Qur’an bil Qur’an mengajak umat Islam untuk kembali menjadikan Al-Qur’an sebagai pusat gravitasi keberagamaan. Tradisi riwayat memiliki nilai historis dan pedagogis, namun tidak dapat menggantikan atau menandingi otoritas wahyu.
Dengan menjadikan Al-Qur’an sebagai saksi atas dirinya sendiri, umat diajak untuk beragama secara sadar, kritis, dan bertanggung jawab—sebuah sikap yang justru menjaga kemurnian tauhid dan memperkuat makna ketaatan itu sendiri. (syahida)
Catatan Redaksi:
Artikel ini merupakan refleksi keagamaan berbasis kajian Al-Qur’an dan tidak dimaksudkan untuk menafikan keragaman pandangan dalam tradisi Islam, melainkan membuka ruang dialog yang sehat dan berlandaskan wahyu.