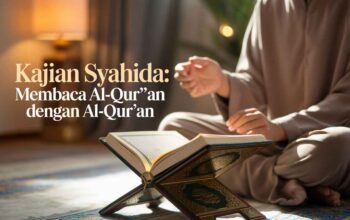Jakarta|PPMIndonesia.com- Dalam kehidupan modern, manusia sering memosisikan dirinya sebagai pusat semesta: penilai, pengatur, bahkan hakim atas segala sesuatu. Kita menghakimi alam, menilai peristiwa, dan memberi vonis moral atas apa yang kita lihat—termasuk ketika menyaksikan hewan yang tampak menderita.
Namun Al-Qur’an mengajukan satu pertanyaan mendasar kepada nurani manusia: siapakah sebenarnya yang lebih memahami realitas—makhluk yang terus bertasbih kepada Tuhan, atau manusia yang sering menilai hanya berdasarkan apa yang tampak di mata?
Tulisan ini merupakan kajian syahida, sebuah kesaksian iman dan refleksi rasional, dengan pendekatan Qur’an bil Qur’an, untuk menimbang ulang relasi antara hewan yang bertasbih dan manusia yang gemar menghakimi.
Hewan dalam Al-Qur’an: Bukan Objek, tetapi Subjek Ibadah
Al-Qur’an tidak pernah menggambarkan hewan sebagai makhluk pasif atau tanpa makna. Justru sebaliknya, mereka ditempatkan sebagai bagian dari kosmos yang hidup dalam kesadaran ketundukan kepada Allah:
وَإِن مِّن شَىْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَـٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ
“Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu tidak memahami tasbih mereka.”
(QS. Al-Isrā’ [17]: 44)
Ayat ini mengandung dua pesan besar. Pertama, semua makhluk hidup berada dalam ibadah. Kedua, manusia memiliki keterbatasan epistemik: kita tidak memahami cara ibadah makhluk lain.
Dengan kata lain, ketidaktahuan manusia tidak boleh berubah menjadi vonis moral atas pengalaman batin makhluk lain.
Ketika Persepsi Menjadi Vonis
Manusia sering kali menyamakan apa yang terlihat dengan apa yang sebenarnya terjadi. Padahal Al-Qur’an berulang kali menegaskan bahwa persepsi manusia dapat menipu.
Dalam kisah Nabi Isa عليه السلام, Allah berfirman:
وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَـٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ
“Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh itu) diserupakan bagi mereka.”
(QS. An-Nisā’ [4]: 157)
Orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu merasa yakin bahwa mereka telah menyiksa dan membunuh Isa. Namun Allah menegaskan bahwa keyakinan itu keliru. Apa yang tampak nyata bagi manusia ternyata bukan realitas yang sesungguhnya.
Ayat ini meletakkan prinsip Qur’ani yang sangat penting:
tidak semua yang tampak sebagai penderitaan benar-benar dialami sebagai penderitaan.
Ibrahim dan Api: Ketika Hukum Alam Ditangguhkan
Prinsip ini ditegaskan secara dramatis dalam kisah Nabi Ibrahim عليه السلام. Ketika ia dihukum dengan api, Allah berfirman:
قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
“Kami berfirman: Wahai api, jadilah engkau dingin dan membawa keselamatan bagi Ibrahim.”
(QS. Al-Anbiyā’ [21]: 69)
Api secara lahiriah tetap menyala. Orang-orang yang menyaksikan mengira Ibrahim sedang disiksa dengan cara paling kejam. Namun Allah mencabut sifat menyakitkan dari api itu.
Di sinilah Al-Qur’an mengajarkan bahwa Allah berkuasa memisahkan kondisi fisik dari pengalaman rasa sakit.
Hewan, Penderitaan, dan Keterbatasan Penilaian Manusia
Ketika manusia melihat hewan diterkam pemangsa, disembelih, atau mati dalam kondisi ekstrem, sering kali muncul vonis spontan: hewan itu pasti menderita hebat.
Namun Al-Qur’an tidak pernah menyatakan bahwa hewan mengalami penderitaan batiniah sebagaimana yang dibayangkan manusia. Justru yang ditegaskan adalah rahmat Allah yang meliputi segala sesuatu:
وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ
“Dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu.”
(QS. Al-A‘rāf [7]: 156)
Dalam dunia medis dan biologi, dikenal kondisi shock fisiologis, di mana makhluk hidup kehilangan sensasi nyeri pada situasi ekstrem. Fakta ini menunjukkan bahwa kerusakan tubuh tidak selalu identik dengan pengalaman rasa sakit.
Di sinilah manusia perlu berhenti sejenak sebelum menghakimi Tuhan atas nama belas kasihan versinya sendiri.
Etika Tetap Tegak: Manusia Tidak Bebas Berlaku Kejam
Menegaskan kemungkinan bahwa hewan dilindungi dari penderitaan batin bukan berarti membenarkan kekerasan. Al-Qur’an dengan tegas melarang segala bentuk agresi:
إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ
“Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 190)
Larangan ini ditujukan kepada manusia, bukan karena hewan pasti menderita, tetapi karena kezaliman merusak jiwa pelakunya sendiri.
Dengan kata lain, etika manusia berdiri independen dari bagaimana Allah melindungi makhluk-Nya.
Siapa yang Sebenarnya Sedang Diuji?
Al-Qur’an justru membalik pertanyaan kita. Bukan “mengapa hewan tampak menderita?”, melainkan:
لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا
“Untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya.”
(QS. Al-Mulk [67]: 2)
Yang sedang diuji bukan hewan, melainkan manusia:
apakah ia rendah hati di hadapan keterbatasan pengetahuannya, atau justru tergesa-gesa menghakimi Tuhan dengan standar emosinya sendiri.
Diamnya Tasbih dan Riuhnya Penghakiman
Hewan bertasbih dalam caranya sendiri—tanpa protes, tanpa tuduhan, tanpa penghakiman. Manusia, sebaliknya, sering kali ribut menilai, menyimpulkan, dan menggugat, bahkan terhadap Tuhan.
Padahal Al-Qur’an telah mengingatkan:
وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا
“Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit.”
(QS. Al-Isrā’ [17]: 85)
Mungkin yang perlu kita lakukan bukanlah lebih cepat menghakimi, melainkan lebih dalam bersaksi—bahwa di balik apa yang tampak kejam, rahmat Allah bekerja dengan cara yang tidak selalu bisa kita pahami. (syahida)