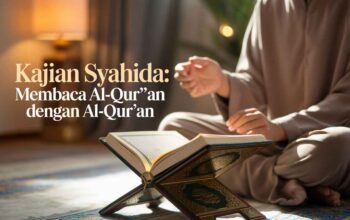Jakarta|PPMindonesia.com– Orang bodoh yang kaya itu ada, sebagaimana orang miskin yang cerdas juga nyata. Keduanya memiliki persoalan dan tantangan masing-masing. Namun, orang kaya yang bodoh kerap memperlihatkan kebingungannya sendiri: ketidakmampuan memanfaatkan kekayaan yang dimiliki secara optimal, bukan hanya untuk kepentingan sosial, tetapi bahkan untuk kebaikan dirinya sendiri.
Kekayaan yang melimpah, tanpa kecerdasan dan kearifan, sering kali hanya berhenti sebagai tumpukan harta. Ia gagal menjadi sumber manfaat, gagal bertransformasi menjadi nilai, apalagi menjadi berkah bagi sesama—termasuk bagi saudara terdekat yang sangat membutuhkan uluran tangan.
Sebaliknya, tidak sedikit orang dengan kondisi ekonomi biasa-biasa saja, bahkan pas-pasan, justru mampu menyantuni anak yatim, mengasuh anak-anak kurang mampu, atau berbagi secara rutin dan ajek dengan penuh keikhlasan. Mereka memberi tanpa pamrih, tanpa perlu sorotan, dan tanpa merasa kehilangan apa pun.
Ironisnya, di sisi lain kita juga mengenal tipe orang kaya yang begitu bakhil. Untuk sekadar mentraktir secangkir kopi pun terasa berat. Sisa makanan pun enggan dibagikan, seolah lebih baik dibiarkan membusuk daripada menjadi manfaat bagi orang lain. Sikap seperti ini mencerminkan kemiskinan batin yang sering kali lebih parah dari kemiskinan materi.
Namun, tentu tidak adil jika semua orang kaya diseragamkan. Ada pula sosok-sosok yang kaya secara materi, cerdas secara nalar, dan lapang secara batin. Mereka memberi bukan untuk mendongkrak nama atau reputasi, apalagi mengeksploitasi kemiskinan orang lain demi citra diri. Apa yang mereka lakukan semata-mata lahir dari empati dan kesadaran kemanusiaan—memberi bahkan sebelum diminta.
Sikap empati semacam ini banyak ditemukan di kalangan aktivis sosial. Mereka memahami betul beratnya perjuangan yang bertumpu pada idealisme, solidaritas, dan rasa senasib sepenanggungan. Bagi mereka, perjuangan bukan alat tunggangi kepentingan, melainkan jalan sunyi untuk membangun kondisi sosial yang lebih adil dan bermartabat.
Sayangnya, tidak semua perjalanan perjuangan bebas dari pengkhianatan nilai. Ada pula mereka yang menjadikan kawan seperjuangan sekadar alat, lalu melupakannya ketika kepentingan telah tercapai. Sejarah pun direduksi menjadi slogan kosong—“Jas Merah” sekadar jargon tanpa kesadaran historis yang hidup.
Padahal, sejarah semestinya menjadi cermin untuk hari ini dan hari esok: ruang refleksi agar masa depan dibangun dengan lebih manusiawi, lebih beretika, dan lebih layak dikenang.
Yang paling sulit dipetakan justru sosok yang miskin secara ekonomi, terbatas secara kecerdasan, dan kurang bijak dalam bersikap. Dalam kondisi seperti itu, pilihan hidup sering kali menjadi beban, bukan jalan. Namun pada akhirnya, semua kembali pada kearifan pribadi: bagaimana kita memosisikan diri, membaca keadaan, dan bertanggung jawab atas sikap kita sendiri.
Sebab wajah sejati kita—kaya atau miskin, pintar atau bodoh—tak pernah bisa dimanipulasi oleh kaca benggala. Ia selalu memantulkan siapa diri kita yang sesungguhnya. (jacob ereste)